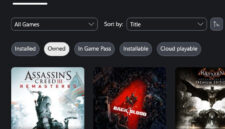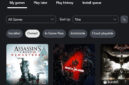Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Panitia Kerja (Panja) Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) telah mencapai kesepakatan penting. Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (10/7) lalu, disepakati untuk mengatur mekanisme hukum modern, yakni plea bargain dan Deferred Prosecution Agreement (DPA), dalam draf KUHAP baru.
Momen bersejarah ini ditandai dengan persetujuan bulat dari seluruh anggota yang hadir, menyusul pertanyaan penegasan dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ketukan palu satu kali oleh Habiburokhman secara resmi mengesahkan pengaturan kedua mekanisme tersebut dalam kerangka hukum acara pidana yang baru.
Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan plea bargain dan DPA, serta bagaimana implikasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
Berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disusun pemerintah, plea bargain atau Pengakuan Bersalah didefinisikan sebagai suatu mekanisme hukum yang memungkinkan Terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana. Pengakuan ini harus diiringi dengan sikap kooperatif selama pemeriksaan, termasuk penyampaian bukti yang mendukung pengakuannya, dengan imbalan berupa keringanan hukuman. Singkatnya, mekanisme plea bargain merupakan langkah strategis bagi terdakwa untuk memperoleh sanksi yang lebih ringan selama ia bersedia mengakui perbuatan pidananya dan bersikap proaktif.
Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab disapa Eddy Hiariej, menjelaskan perbedaan mendasar plea bargain dengan restorative justice. Menurutnya, jika restorative justice berlangsung di luar persidangan, maka plea bargain dan DPA — yang akan dirinci dalam DIM 27 — tetap memerlukan persetujuan hakim. “Jadi hakim yang akan memutuskan apakah plea bargain diterima atau tidak,” ujar Eddy. Apabila diterima, proses persidangan akan berubah dari acara biasa menjadi acara singkat, yang detailnya akan dijelaskan dalam pasal-pasal berikutnya dari RUU KUHAP.
Lebih lanjut, Eddy Hiariej menguraikan bahwa penerapan plea bargain tidak berlaku untuk semua kasus, melainkan terbatas pada terdakwa dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Ia menegaskan bahwa meskipun mendapat keringanan, terdakwa tetap akan dihukum. Sebagai ilustrasi, jika seseorang melakukan penganiayaan berat dengan ancaman pidana 5 tahun dan ia bersedia mengakui kesalahan serta mengganti rugi, Jaksa dapat menuntutnya bukan dengan hukuman maksimal, melainkan diturunkan menjadi 2 tahun. Keputusan akhir mengenai persetujuan plea bargain sepenuhnya ada pada hakim. Bahkan, tidak menutup kemungkinan hakim dapat menjatuhkan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial, mengingat adanya pengakuan bersalah dan kesediaan untuk ganti rugi.
Sementara itu, Deferred Prosecution Agreement (DPA) merupakan substansi baru dalam hukum acara pidana yang diatur dalam RUU KUHAP. Eddy Hiariej menjelaskan DPA sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan Jaksa Penuntut Umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana oleh korporasi. Ini berarti, jika sebuah korporasi terbukti melakukan pencemaran lingkungan yang berdampak pada masyarakat, namun bersedia untuk mengganti rugi serta memperbaiki dampak yang ditimbulkan, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk tidak dilakukan penuntutan.
Sama halnya dengan plea bargain, keputusan penerapan DPA juga tetap berada di tangan hakim, meskipun perjanjian awal dilakukan antara Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa korporasi. Eddy Hiariej menambahkan, apabila korporasi tidak mampu memenuhi syarat-syarat perjanjian penundaan penuntutan tersebut, maka proses hukum akan dilanjutkan secara normal. Mekanisme DPA ini, yang akan diatur secara rinci hingga 17 ayat dalam pasal-pasal KUHAP, memiliki semangat serupa dengan plea bargain, namun secara spesifik ditujukan untuk entitas korporasi dengan syarat-syarat tertentu, terutama berkaitan dengan tindak pidana yang berdampak pada masyarakat dan perekonomian negara.
Hingga saat ini, rapat panja RUU KUHAP masih terus bergulir. Ada lebih dari 1.000 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang harus disepakati oleh Komisi III DPR RI dalam pembahasan mendalam terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini.