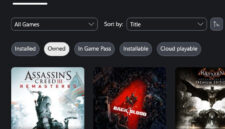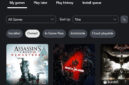Tahun 1986, sebagai pemuda yang penuh rasa ingin tahu, saya pertama kali mengunjungi Makau—kota di bawah pemerintahan Portugis. Makau memikat saya dengan beragam pesona, mulai dari aroma Portuguese Egg Tart di toko roti kuno dekat reruntuhan Gereja Sao Paolo hingga arsitektur kolonial yang berpadu harmonis dengan kuil-kuil Tionghoa. Namun, satu hal yang paling membekas dalam ingatan saya bukanlah bangunan megah, melainkan sesuatu yang berada tepat di bawah kaki saya: pola batu hitam-putih yang berkelok seperti gelombang samudra.
Saya pertama kali menyaksikannya di Largo do Senado, alun-alun utama kota. Lantai tempat saya melangkah bukanlah lantai biasa, melainkan karya seni yang tercipta dari ribuan batu kecil. Desainnya begitu dinamis, seakan-akan air sedang beriak atau pasir tertiup angin. Saat itu, saya tak mengetahui nama maupun sejarahnya, namun pesonanya langsung memikat hati.
Pola serupa juga saya temukan di Rua de So Paulo, jalan menuju reruntuhan Gereja St. Paul, dan di sekitar Avenida de Almeida Ribeiro. Bahkan di taman-taman kecil, trotoar pun ditata dengan motif yang rapi dan artistik. Tanpa sadar, saya melangkah di atas jejak sejarah panjang yang berasal dari belahan dunia lain.
Dari Batu ke Budaya
Sebelum era internet, melalui buku-buku, saya kemudian mengetahui bahwa pola batu tersebut bernama calada portuguesa, atau dalam bahasa Inggris: Portuguese pavement. Teknik ini telah ada sejak zaman Romawi, namun berkembang pesat di Portugal pada abad ke-19. Batu kapur putih dan basalt hitam dirangkai dengan tangan oleh para pengrajin, membentuk pola-pola ombak, bunga, bahkan kapal.
Puncak popularitas calada terjadi saat digunakan untuk merekonstruksi Rossio Square di Lisboa pasca gempa bumi besar tahun 1755. Dari situ, teknik ini menyebar ke wilayah jajahan Portugis: Brasil, Mozambik, Goa, dan tentu saja, Makau. Di Makau, penggunaan calada portuguesa meningkat pesat pada akhir abad ke-19, terutama di pusat kota. Meski sempat tergantikan oleh aspal dan trotoar modern, pada era 1980-an, calada kembali dihidupkan sebagai bagian identitas kota.
Menariknya, setelah Makau kembali ke Tiongkok pada 1999, calada tetap dilestarikan. Para pengrajin lokal bahkan dilatih langsung oleh ahli dari Portugal untuk menjaga keaslian tekniknya. Ini bukan sekadar tentang batu, melainkan tentang pelestarian warisan budaya yang melampaui batas negara dan waktu.
Pertemuan Kedua: Lisboa dan Sintra
Bertahun-tahun kemudian, saya akhirnya mengunjungi Lisboa, tanah asal calada portuguesa. Pertemuan ini terasa seperti bertemu kembali dengan kenangan lama yang tersimpan dalam alam bawah sadar. Saya lebih menyukai nama Lisboa daripada Lisbon, mengingat kenangan pertama saya tentang nama tersebut berasal dari Casino Lisboa di Makau.
Di jantung Lisboa, di Praca do Rossio, saya kembali berdiri di atas pola gelombang yang sama seperti di Makau. Namun kali ini, saya memahami sejarahnya, mendengar kisah-kisah dari pemandu wisata. Saya mengerti mengapa batu-batu itu hitam dan putih, mengapa berbentuk gelombang, dan siapa yang merangkai keindahan tersebut. Saya menyusuri Avenida da Liberdade, mengagumi motif bunga dan daun di trotoar. Di Baixa dan Chiado, pola geometris menghiasi jalan-jalan sempit yang dipenuhi toko buku dan kafe.
Selanjutnya, saya mengunjungi Belém, kawasan bersejarah di tepi Sungai Tagus. Di Praca do Comércio, lantai dihiasi calada dengan gambar kapal, kompas, dan motif maritim lainnya. Di sini, saya merasakan calada bukan hanya bagian lanskap, tetapi cerminan jiwa bangsa pelaut Portugis, penjelajah tujuh samudra.
Dari Lisboa, saya melanjutkan perjalanan ke Sintra, kota dongeng di kaki pegunungan. Jalan menuju Palacio Nacional da Pena, yang dikenal sebagai Calcada da Pena, merupakan jalur berbatu dengan pemandangan hutan dan kabut yang menyelimuti kastil di atas bukit. Di Centro Histórico, calada menghiasi trotoar di depan toko-toko dan restoran kecil. Rasanya seperti berjalan di atas permadani batu yang menghubungkan masa lalu dan masa kini.
Peta Batu Dunia
Jejak calada portuguesa ternyata tak hanya ada di Portugal dan Makau. Di Brasil, trotoar sepanjang Copacabana Beach menggunakan pola ombak yang terkenal. Di Luanda (Angola) dan Maputo (Mozambik), calada menghiasi alun-alun utama kota. Bahkan di beberapa sudut kota seperti Paris dan New York, komunitas Portugis memperkenalkan keindahan ini ke ruang publik.
Calcada menjadi bukti bahwa seni dan budaya mampu menjelajah jauh melampaui batas politik. Ia bukan sekadar untuk diinjak—ia menginjak kembali memori, menghubungkan kota dan kisah, menyatukan gaya dan sejarah.
Menjaga Langkah
Namun, keindahan ini juga menghadapi tantangan. Banyak kota mempertanyakan kelayakan calada di era modern. Ada yang menganggapnya licin saat hujan atau tidak ramah bagi pengguna kursi roda. Ada usulan untuk menggantinya dengan permukaan yang lebih praktis. Namun, banyak warga menolak: bagaimana mungkin kita mengganti sejarah berabad-abad dengan aspal abu-abu?
Di Lisboa, para tukang batu—calceteiros—masih mempertahankan tradisi ini. Mereka adalah seniman jalanan sejati, merangkai batu demi batu, melukis kota dengan tangan dan palu kecil. Di Makau, para tukang lokal dilatih untuk menjaga warisan ini agar tidak hilang ditelan zaman.
Langkah yang Berarti
Saat mengenang langkah kaki saya di Makau tahun 1986, saya menyadari bahwa saat itu saya tengah berjalan di atas jembatan tak kasatmata—jembatan antara timur dan barat, antara masa lalu dan masa depan. Saya tidak tahu namanya saat itu, namun calcada portuguesa telah menjadi bagian dari memori visual dan emosional saya.
Kini, setiap kali saya melihat trotoar batu hitam-putih bergelombang, hati saya tersenyum. Ada kisah panjang yang tersembunyi di balik setiap batu kecil itu. Kisah tentang pelayaran, tentang koloni dan kemerdekaan, tentang kota-kota yang berbeda namun terhubung oleh jejak yang sama.
Dan kisah itu, seperti calada itu sendiri, masih terus dilangkahi.