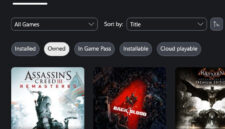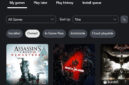Konsep keadilan restoratif, yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), menuai kritik tajam dan disebut salah kaprah. Alih-alih memprioritaskan keadilan bagi korban kejahatan, terutama perempuan yang menjadi korban tindak pidana seperti perkosaan dan kekerasan, konsep ini justru dikhawatirkan hanya akan menguntungkan penegak hukum dan pelaku, sehingga menyulitkan korban menemukan keadilan.
Kritik tersebut berpusat pada Pasal 74 RUU KUHAP, di mana pemerintah dan anggota dewan mengatur bahwa keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan. Namun, pengaturan ini dianggap ganjil karena penekanan pada penyelesaian di luar persidangan dinilai dapat menggeser esensi keadilan restoratif yang seharusnya berfokus pada pemenuhan hak dan kepentingan korban.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengungkapkan kekhawatiran bahwa pengaturan keadilan restoratif ini hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola kelebihan beban kerja peradilan. “Selesaikan saja di luar persidangan—penegak hukum jatuhkan sanksi. Ini yang untung adalah penegak hukum dan pelaku. Enggak ada urusan sama korban,” tegas seorang peneliti dari Indonesia Judicial Research Society.
Di sisi lain, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Hiariej, sebelumnya menyatakan bahwa perubahan KUHAP didasarkan pada keinginan untuk mentransformasi hukum pidana di Indonesia. Menurutnya, hukum pidana tidak lagi semata-mata menjadi sarana balas dendam, melainkan pemberi keadilan korektif hingga restoratif. “Kita harus beralih ke sistem yang lebih modern dengan mengedepankan keadilan korektif, restoratif, dan fasilitatif,” ujarnya pada Januari 2025. Edward menekankan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan faktor keadilan, keseimbangan, serta kepentingan masyarakat dan korban.
Bagaimana keadilan restoratif bekerja?
Menurut buku pedoman berjudul Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (2022) yang dipublikasikan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), keadilan restoratif didefinisikan sebagai pendekatan penanganan tindak pidana yang mengutamakan korban. Dalam praktiknya, pendekatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk korban, pelaku, dan unsur terkait lainnya, dengan tujuan utama mengupayakan pemulihan korban, bukan semata-mata pembalasan.
Keadilan restoratif memiliki beberapa prinsip dasar yang krusial untuk dipahami:
- Pertama, penerapannya tidak secara otomatis menghentikan perkara yang sedang diusut.
- Kedua, pendekatan ini mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan yang dipengaruhi oleh usia, latar belakang sosial, pendidikan, hingga ekonomi.
- Ketiga, pelaksanaannya harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari semua pihak.
- Keempat, prosesnya didasarkan pada kesukarelaan tanpa paksaan maupun tekanan.
- Kelima, khususnya dalam kasus anak, tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik anak yang bersangkutan.
Di Indonesia, ketentuan mengenai keadilan restoratif telah termuat dalam berbagai regulasi, mulai dari undang-undang hingga peraturan kepolisian. Namun, ICJR menganalisis bahwa titik tolak implementasi keadilan restoratif dalam regulasi yang ada masih berorientasi pada “penyelesaian perkara.” Hal ini menyebabkan keadilan restoratif ditempatkan secara terbatas sebagai “tujuan atau hasil” akhir, alih-alih kombinasi “proses dan tujuan.”
Paradigma bahwa keadilan restoratif merupakan solusi akhir dari kasus pidana sempat mengemuka dalam insiden penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak, Mario Dandy. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta sempat menawarkan keadilan restoratif dalam menangani kasus kekerasan ini, dengan catatan keputusan akhir berada di tangan keluarga korban. Namun, ide tersebut ditentang oleh publik, dan Kejati Jakarta kemudian menarik opsi keadilan restoratif tersebut.
Kecenderungan pemanfaatan keadilan restoratif sebagai “tujuan” juga terlihat dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, di mana penyelesaian kasus dibatasi mekanismenya melalui klausul “melalui perdamaian.” Peneliti hukum Matheus Nathanael dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menyoroti bahwa RUU KUHAP melanjutkan perspektif berlandaskan hasil akhir—yakni tuntasnya kasus.
Matheus Nathanael menjelaskan bahwa keadilan restoratif, dalam pengertian sesungguhnya, tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana yang berlaku di banyak negara seperti Inggris. Di sana, keadilan restoratif diberikan setelah keputusan hakim. Pemberlakuan keadilan restoratif pasca putusan hakim menunjukkan bagaimana negara merespons kondisi korban yang mungkin berada dalam bayang-bayang kekecewaan, ketidakpastian, atau ketidakpuasan. Melalui mediasi, keinginan korban yang belum terpenuhi dapat diwujudkan tanpa menghapus vonis yang diberikan kepada tersangka. “Jadi memang keadilan restoratif dan penjatuhan pidana itu bisa berjalan paralel,” tegasnya saat diwawancarai BBC News Indonesia.
Namun, Matheus menyoroti bahwa realita di Indonesia berbeda. RUU KUHAP menetapkan bahwa keadilan restoratif mengarah pada penuntasan kasus di luar persidangan, sehingga antara keadilan restoratif dan pemberian hukuman “tidak mungkin berlangsung secara beriringan.” Menurutnya, “Kalau perkaranya enggak disidang, berarti tidak dijatuhi hukuman.”
Hasil Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP yang dirumuskan DPR, khususnya Pasal 78 ayat (1), memungkinkan pelaku dan korban untuk membuat kesepakatan “menyelesaikan perkara” di hadapan penyelidik atau penyidik. Kesepakatan ini dibuktikan dengan surat penyelesaian perkara di luar pengadilan yang ditandatangani oleh pelaku, korban, serta penyelidik atau penyidik. Berdasarkan surat tersebut, penyelidik atau penyidik dapat menerbitkan surat penghentian penyelidikan atau penyidikan, mengakhiri proses kasus.
Praktik semacam ini, menurut Matheus, akan mereduksi penyelesaian hukum yang berkeadilan. Selain itu, akan menancapkan persepsi kuat bahwa semua perkara pidana dapat ditebus dengan “ganti rugi” tanpa perlu menjalani hukuman penjara. “Akhirnya, tidak menutup kemungkinan, yang muncul berikutnya adalah pengusutan kasus yang transaksional,” tegas Matheus.
Matheus menerangkan bahwa ada dua kepentingan yang saling bertemu dalam situasi ini. Pertama, kepentingan aparat penegak hukum untuk mencegah penumpukan kasus. Kedua, kepentingan pelaku untuk menghindari persidangan dan catatan kriminal yang akan menempel padanya. “Ada criminal record yang terus dia tanggung. Makanya, dia biasanya menawarkan diri ke penegak hukum untuk tidak diadakan persidangan. Bayar sanksi atau ganti rugi saja kepada korban,” tutur Matheus. “Nah, di situlah aparat penegak hukum mulai berpikir kalau kasus ini, sepertinya, enggak penting-penting banget untuk disidang.”
Kewenangan aparat penegak hukum menjadi sangat besar karena mereka menjadi aktor tunggal di setiap tahapan, mulai dari penyidikan hingga penuntutan. Matheus menyebutnya sebagai monopoli. Keberhasilan atau kegagalan penerapan keadilan restoratif hanya disandarkan pada pandangan masing-masing personel dari institusi yang berwenang. Di tahap penyidikan, polisi memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif atau tidak, begitu pula kejaksaan di tahap penuntutan. “Urusan restorative justice itu, pada ujungnya, dimonopoli oleh setiap institusi di tahapan masing-masing, dan ini sudah pasti ada transaksi,” kata Matheus.
Demi mengantisipasi terjadinya jual-beli kasus, Matheus menegaskan bahwa wajib hukumnya menyertakan partisipasi pihak lain yang mampu mengintervensi dan meninjau apakah pendekatan keadilan restoratif ditempuh melalui proses yang baik. “Siapakah dia? Pengadilan. Kalau restorative justice-nya disetujui, maka harus dibawa ke pengadilan supaya hakim bisa memeriksa,” tambahnya. “Jadi, setiap urusan itu harus diurus lebih dari satu institusi. Kalau tidak, korup.”
Potensi buruknya tidak hanya itu. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mengungkapkan bahwa mekanisme keadilan restoratif yang dibuka sejak tahap penyelidikan memperbesar pintu “rekayasa kasus.” Ketua Umum PBHI, Julius Ibrani, menjelaskan kepada BBC News Indonesia bahwa tahap penyelidikan adalah proses awal untuk memastikan suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. “Pada tahap ini, belum ada tersangka, belum ada dua alat bukti, dan belum ada kepastian bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana,” jelasnya. “Maka, membuka ruang restorative justice di titik ini sama saja dengan berupaya menyelesaikan suatu kejahatan yang bahkan belum pasti ada.”
Konsekuensi yang sangat mungkin terjadi setelahnya adalah penyelidik “menargetkan orang untuk berhadapan secara hukum” demi mengakhiri pengusutan perkara. Tak jarang, korban rekayasa kasus ini berasal dari kelompok ekonomi atau sosial yang lebih rendah dibandingkan pelaku. Data KontraS menunjukkan terdapat 27 dugaan rekayasa kasus yang dilakukan Polri sepanjang 2019 hingga 2022, tersebar di 15 provinsi dan muncul dari tingkat polsek hingga polda. Korban rekayasa kasus, menurut KontraS, didominasi masyarakat sipil dengan contoh mulai dari salah tangkap, upaya mencari pengakuan yang dibarengi penyiksaan, hingga tidak membawa surat tugas saat meringkus korban. Penyelewengan ini tidak lepas dari posisi kepolisian yang melekat pada fungsi penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka.
Posisi rentan kelompok perempuan
Aktivis dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumenep, Nunung Fitriana, mewanti-wanti agar penerapan pendekatan keadilan restoratif tidak semakin menyudutkan kelompok perempuan. Nunung menerangkan bahwa praktik keadilan restoratif tidak sedikit digunakan untuk menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Relasi antara pelaku dan korban dalam KDRT terbangun dari ikatan seperti pernikahan, yang kemudian membuat korban “susah meneruskan ke jalur hukum,” ucap Nunung. “Untuk [kasus] mencuat, terus melapor atau meminta pertolongan saja itu, rata-rata, kalau korban KDRT itu harus sudah [mengalami] kejadian yang kesekian kali,” ujarnya saat dihubungi BBC News Indonesia. “Jadi, sangat jarang KDRT itu dilaporkan kalau itu kejadian yang pertama.”
Di sinilah, Nunung melanjutkan, “opsi damai” sering dipilih karena jika dibawa ke ranah hukum akan menjadi aib bagi semua pihak, termasuk keluarga besar. Meskipun demikian, pemberlakuan keadilan restoratif dalam konteks KDRT tidak serta-merta menjauhkan korban dari bahaya. Nunung mengisahkan pernah mendampingi korban KDRT yang sepakat berdamai tanpa sepengetahuan kepolisian atau pihak ketiga. “Jadi, kalau ada kasus KDRT itu polisi, selain menyidik, akan membuka opsi damai, memang,” ucap Nunung. “Cuma, keputusan damai itu kemudian korban dan pelaku yang memutuskan sendiri.” Tragisnya, berjarak sebentar dari kesepakatan tersebut, korban tewas di tangan pelaku.
Dengan pemberlakuan keadilan restoratif versi RUU KUHAP yang dikritik para aktivis dan pegiat hukum karena begitu lentur, Nunung meminta aparat kepolisian tidak sembarangan meloloskan pendekatan ini. Menurutnya, meskipun keadilan restoratif diberlakukan, aparat harus tetap melihat peluang ancaman terhadap korban. “Kalau dari sisi pendamping, gitu, benar-benar harus jeli dan objektif. Apakah peluang restorative justice ini baik atau tidak untuk korban?” sebut Nunung. “Jangan-jangan dia [pelaku] memberikan opsi restorative justice hanya untuk mengendalikan situasi. Nanti ketika ada potensi lagi, dia kembali melakukan kekerasan. Jadi, itu sesuatu yang harus diwaspadai semua pihak.”
Dalam praktiknya, pembahasan keadilan restoratif yang mendudukkan korban dan pelaku tidak dapat ditempuh sendirian; harus ada penengah—bukan hanya polisi, melainkan juga keluarga serta pendamping. Keberadaan penengah ditujukan agar bisa membantu menyusun poin-poin yang disetujui kedua belah pihak, di samping menawarkan pertimbangan-pertimbangan yang fokusnya melindungi korban. “Itu yang diperbarui, yang disepakati, yang menjadi prasyarat agar restorative justice itu terjadi. Salah satu penekanan [kepada pelaku] adalah tidak akan melakukan kekerasan lagi,” tambah Nunung. Jalan yang tersedia untuk keadilan restoratif dalam kasus KDRT memang panjang, dan Nunung meyakini itu sebagai cara supaya hak-hak korban terjaga. Namun, dengan ketentuan baru yang terpacak di RUU KUHAP, Nunung tak bisa menutup kekhawatirannya.
Merujuk DIM RUU KUHAP yang sudah dibahas DPR, mekanisme keadilan restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang diancam penjara paling lama lima tahun (Pasal 74A). Kekerasan fisik yang menyebabkan luka ringan memenuhi kriteria tersebut. Ketika ada korban yang membawa kekerasan ini ke ranah hukum, penyelesaian tanpa persidangan melalui keadilan restoratif dapat diterapkan. Persoalannya, pada Pasal 78 ayat (1), pelaku dan korban dapat bersepakat untuk menghentikan perkara hanya di hadapan penyelidik atau penyidik—tidak tertulis adanya pihak ketiga. Padahal, Nunung menggarisbawahi, keadilan restoratif yang diupayakan dengan menihilkan keberadaan pihak ketiga atau keluarga dan orang tua “sangat berisiko.” “Bisa jadi korban justru mengalami kekerasan yang lebih parah,” ucapnya.
Koordinator Divisi Advokasi dan Kebijakan LBH Apik Jakarta, Piu, menambahkan bahwa dengan hanya mempersilakan korban serta pelaku bertemu dalam satu ruang, tanpa pihak ketiga atau pendamping, keadilan untuk korban otomatis tidak terjamin. Pasalnya, korban harus mengulang kembali traumanya, dan dialog yang tercipta pun “sudah tidak berada di posisi yang setara.” Korban, pada saat bersamaan, juga rentan diancam dan diintimidasi. “Terkhusus untuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender, perempuan memiliki trauma-trauma yang cukup melekat pada diri masing-masing,” jelasnya. “Dan kita harus memperhatikan juga ketika kemudian restorative justice itu dilakukan, mempertemukan korban dengan pelaku, tentu trigger-nya terhadap trauma itu pasti akan muncul.”
Hal ini lantas, sebut Piu, memperlihatkan proses keadilan restoratif itu hanya dimaknai sebagai “perdamaian” terhadap pelaku. Piu menegaskan bahwa konsep keadilan restoratif, terutama jika dihubungkan dengan kekerasan berbasis gender, tidak dapat diartikan semata sebagai “perundingan.” Ketika membahas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, keadilan restoratif tidak boleh menghapus sanksi pidana bagi pelaku sebab “itu bagian dari kepastian hukum untuk perempuan korban,” terang Piu. Berikutnya, ganti rugi bagi korban tetap menjadi kewajiban pelaku, sesuai dengan dampak-dampak yang diderita korban. Tak ketinggalan, guna mencapai “keadaan semula,” seperti salah satu nilai dasar keadilan restoratif, pelaku harus menjalani rehabilitasi dengan maksud tidak mengulangi lagi perilaku jahatnya. “Keadaan semula di sini dalam arti keadaan yang tanpa adanya pelanggaran terhadap hak atau pelanggaran tindak pidana di masyarakat. Kalau dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, ini supaya tidak ada lagi keberulangan ke korban,” tandas Piu.
Draf RUU KUHAP yang dipublikasikan DPR pada Maret 2025 tidak memuat satu pun poin kekerasan terhadap perempuan sebagai ketentuan yang dikecualikan dari mekanisme keadilan restoratif. Baru pada DIM yang diusulkan pemerintah, frasa “tindak kekerasan seksual” masuk dalam pengecualian penerapan keadilan restoratif. Komnas Perempuan, melalui rekomendasinya, meminta pemerintah dan DPR menyertakan “tindak pidana perkosaan” serta “tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 5 tahun tapi dilakukan lebih dari satu kali atau berulang” ke dalam daftar perkara yang tidak berlaku penerapan keadilan restoratif. Selain itu, Komnas Perempuan turut pula mendesak otoritas untuk menyertakan tambahan bahwa korban wajib didampingi pendamping atau advokat tatkala proses keadilan restoratif dijalankan.
Komnas Perempuan menerangkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan masih sangat dipengaruhi oleh stereotip gender yang berakar pada nilai diskriminasi. Efeknya, posisi perempuan dalam sistem hukum menjadi sangat rapuh hanya karena identitas mereka. Piu berharap pemerintah, sebelum benar-benar mengesahkan KUHAP yang nantinya akan memengaruhi penanganan pidana, lebih dulu mengkaji ulang bagaimana konsep keadilan restoratif dimaknai secara luas oleh aparat penegak hukum. “Jangan sampai restorative justice justru malah menjauhkan korban dari akses keadilan dalam proses peradilan pidana,” pungkasnya.
Senada, Direktur Women’s Crisis Center Jombang, Ana Abdillah, menilai bahwa pelaksanaan proses formal (pemahaman) di antara aparat penegak hukum ihwal keadilan restoratif “berat sekali.” Belum lagi, dia menambahkan, “metode pengawasannya yang sangat lemah.” “Sehingga, misalnya, dalam konteks penanganan kekerasan kepada perempuan, banyak hak-hak korban yang gagal diperjuangkan,” terang Ana.
Ahmad Mustofa di Madura berkontribusi dalam laporan ini.
- RUU KUHAP – Pasal-pasal dinilai bermasalah dan 1.676 DIM selesai dibahas dalam dua hari
- Kontroversi RUU Polri dan RUU KUHAP – Apa saja yang bermasalah dan poin apa yang seharusnya dimuat?
- Demo mahasiswa: Lini masa ‘perang tagar’ antara demonstran dan propemerintah di Twitter
- Mengapa permintaan tambahan anggaran Polri menuai polemik?
- Sedikitnya 100 nyawa diduga melayang di tangan polisi dalam tiga tahun terakhir – ‘Mereka bukan sekadar angka, tapi nyawa manusia’
- Kisah korban rekayasa kasus polisi: ‘Enggak ngaku begal, saya ditembak. Padahal saya enggak ngelakuin’
- DPR sahkan Revisi UU TNI, mahasiswa gelar demonstrasi di berbagai kota – ‘Demokrasi telah dibunuh di DPR’
- Potret kinerja DPR 2017: Kasus korupsi, kepemimpinan dan gagal penuhi target
- DPR ‘paling korup’ menurut persepsi masyarakat Indonesia
- Rencana pengesahan RKUHP, pakar hukum tata negara: ‘Prosesnya cacat formil’
- RKUHP disahkan: Pemerintah persilakan tempuh jalur hukum, pegiat demokrasi khawatir Indonesia kembali ke era Orde Baru
- ‘Apakah berani polisi mengatakan ‘Maaf Pak Presiden laporan Anda tak beralasan’, Pasal penghinaan presiden di RUU KUHP ‘dituntut dihapus’