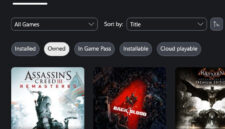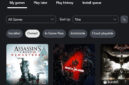Lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara kolektif menyuarakan harapannya agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Keadilan Iklim. Regulasi ini dinilai sangat vital untuk mengarahkan transisi energi di Indonesia agar berlangsung secara berkeadilan, tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat.
Peneliti Indonesia Center Environment Law (ICEL), Sylvi Sabrina, mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki 13 regulasi terkait transisi energi. Namun, hasil temuan ICEL menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada belum mampu menjawab kompleksitas isu transisi energi yang mencakup berbagai sektor kehidupan. Transisi energi yang adil dipahami sebagai sebuah proses inklusif yang memastikan ‘tak ada yang tertinggal’, sebuah prinsip fundamental yang diperkuat oleh RUU Keadilan Iklim.
“RUU ini berpotensi menjadi instrumen hukum utama untuk mewujudkan transisi energi yang adil,” tegas Sylvi dalam acara Kick-off Local Conference of Youth di Jakarta, Jumat (11/7). Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pengesahan regulasi ini juga akan menjadi bukti konkret komitmen Indonesia di panggung global dalam mengatasi krisis iklim. Pentingnya RUU ini tidak hanya terbatas pada upaya penurunan emisi CO2, melainkan juga menyangkut mitigasi ketimpangan sosial yang mungkin timbul akibat perubahan lanskap energi.
Saat ini, Rancangan Undang-Undang Keadilan Iklim, yang juga dikenal sebagai RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, telah resmi masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025.
Transisi Energi Tak Berkeadilan bisa Ciptakan Pengangguran
Sylvi menyoroti adanya beberapa indikasi ketidakadilan dalam proses transisi energi yang sedang berjalan. Fenomena ini nyata terlihat, salah satunya, di sekitar area Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang direncanakan akan dipensiunkan.
Contoh konkret adalah para pekerja di PLTU Cirebon. Meskipun informasi mengenai rencana pensiun PLTU sudah tersebar, Sylvi menyayangkan belum adanya inisiatif dari pihak perusahaan untuk menyediakan program pelatihan atau alih profesi bagi para pekerja yang akan terdampak. Ketiadaan persiapan ini berpotensi besar menciptakan masalah pengangguran massal, mengingat para pekerja akan kehilangan mata pencarian utama mereka ketika PLTU dinonaktifkan. Oleh karena itu, program pelatihan menjadi krusial untuk membekali mereka menghadapi perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi.
Indikasi ketidakadilan lain muncul dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur, yang melintasi wilayah Kabupaten Gayo Lues, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Proyek PLTA berkapasitas 443 MW ini direncanakan akan membangun bendungan seluas 193,5 hektare, dengan perkiraan akan menenggelamkan Desa Lesten di Gayo Lues. Mirisnya, warga yang terdampak relokasi mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai lokasi relokasi baru, proses pemindahan, maupun hak-hak dan fasilitas yang akan mereka terima. Selain itu, dokumen AMDAL proyek ini hanya membahas mitigasi konflik satwa liar dengan metode penggiringan, tanpa pendekatan perlindungan yang memadai, padahal area tersebut merupakan habitat kunci bagi spesies terancam punah seperti orangutan, gajah, dan harimau Sumatra.
Kasus serupa juga terjadi pada proyek PLTA Poso di Sulawesi Tengah, yang berpotensi menimbulkan konflik serius dengan masyarakat adat. Dampak yang telah terlihat meliputi perampasan tanah, timbulnya konflik antarwarga, pemberian ganti rugi yang tidak adil, kerusakan lingkungan yang parah, hingga peningkatan angka kemiskinan di kalangan masyarakat terdampak.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji, menambahkan bahwa transisi energi juga berpotensi membawa dampak lingkungan yang beragam. Berdasarkan pemantauan Greenpeace Indonesia, pemanfaatan energi dan konsekuensinya tidak merata di setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa transisi energi benar-benar berjalan secara adil dan berkelanjutan. Masyarakat harus proaktif dalam menyuarakan kepentingan dan hak-hak mereka.
“Jika kita tidak berjuang untuk merebut mikrofonnya, maka selamanya kita akan terpinggirkan dan kehilangan suara kita,” pungkas Sekar, menekankan pentingnya advokasi dan keterlibatan publik dalam proses transisi energi ini.