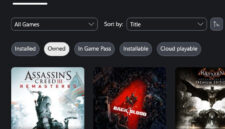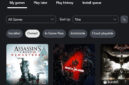Kabar mengenai rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Peta Jalan Kecerdasan Buatan (AI) di Indonesia menjadi sorotan penting. Langkah ini mengindikasikan kesadaran pemerintah akan urgensi regulasi AI. Namun, bagi praktisi yang telah berkecimpung di dunia internet sejak 1995, berita ini turut membangkitkan kembali kekhawatiran lama: akankah kita kembali terjerat dalam lingkaran “telat mikir” yang pernah menghambat laju inovasi di masa lalu?
Pengalaman pahit di awal milenium baru menjadi cermin buram. Saya menyaksikan langsung bagaimana inovasi dapat terhadang oleh tembok regulasi yang kaku. Layanan Voice over Internet Protocol (VoIP), yang sejatinya merupakan kapabilitas inheren dari teknologi internet, kala itu justru dibatasi bahkan dilarang bagi Penyelenggara Jasa Internet (PJI). Padahal, VoIP berpotensi merevolusi komunikasi dan menekan biaya bagi masyarakat luas.
Ironisnya, dasar hukum yang digunakan saat itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sama sekali tidak menyebut kata “internet”. Ketiadaan payung hukum yang jelas, ditambah pemahaman yang kurang memadai tentang teknologi yang berkembang pesat, mendorong pemerintah mengambil langkah yang justru mematikan inisiatif inovatif. Akibatnya fatal: masyarakat tetap harus membayar mahal untuk layanan suara, sementara peluang industri teknologi untuk berkembang lebih pesat terhambat signifikan.
Regulasi spesifik terkait internet baru muncul pada tahun 2001 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001, yang itupun lebih fokus mengatur infrastruktur. Sementara itu, payung hukum yang mencakup ranah aktivitas daring secara lebih luas, mulai dari transaksi elektronik hingga potensi penyalahgunaan informasi, baru terwujud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tahun 2008. Ini adalah langkah yang menurut pandangan saya, amat sangat terlambat.
Kekhawatiran Terulang di Era AI: Ancaman Ekonomi dan Kohesi Sosial
Mencermati pengalaman masa lalu, kekhawatiran terbesar saya kini terarah pada era Kecerdasan Buatan (AI) yang melaju begitu pesat. Sejarah kelam bisa saja terulang. AI berkembang jauh lebih cepat dan memiliki implikasi yang jauh lebih luas daripada teknologi internet di masa lalu. Meskipun Perpres AI akan diterbitkan, kekhawatiran muncul karena peraturan turunan ini kemungkinan besar akan mengacu pada undang-undang yang lebih umum seperti UU ITE atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Pendekatan menggunakan kedua undang-undang tersebut sebagai payung hukum untuk Perpres AI terkesan “memaksakan”, sebab substansi AI jauh lebih luas dan kompleks dibandingkan lingkup asli kedua UU tersebut. Situasi ini berpotensi menciptakan ambiguitas hukum dan celah interpretasi di kemudian hari, mirip dengan bagaimana UU Telekomunikasi tahun 1999 gagal mengakomodasi internet dengan baik.
Ini adalah skenario “telat mikir” yang paling mencemaskan, karena dampaknya bisa berlipat kali lebih merusak:
1. Peluang Ekonomi Bernilai Tinggi yang Terhambat
AI adalah gelombang inovasi berikutnya yang akan merevolusi hampir setiap sektor ekonomi. Jika regulasi tidak segera hadir atau justru menghambat, Indonesia berisiko kehilangan potensi investasi dan talenta terbaik dalam ekosistem AI. Investor, baik lokal maupun asing, akan ragu menanamkan modal di lingkungan pengembangan AI yang tidak memiliki kepastian hukum. Akibatnya, talenta AI terbaik kita mungkin akan memilih berkarya di negara-negara dengan kerangka regulasi AI yang lebih jelas dan mendukung, membuat kita tertinggal dalam perlombaan teknologi global.
Ketiadaan panduan yang jelas juga akan membendung inovasi lokal. Para pengembang AI akan ragu berinvestasi atau menciptakan solusi baru, takut melanggar aturan yang belum ada atau tidak jelas. Kita akan kehilangan kesempatan emas untuk memanfaatkan AI guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor vital, mulai dari kesehatan hingga pertanian, menjadikan kita hanya konsumen teknologi AI dari luar.
2. Potensi Problematika Kohesi Sosial yang Mendesak
Selain kerugian ekonomi, absennya regulasi AI yang memadai juga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial yang mengancam kohesi masyarakat:
-
Penyebaran Disinformasi dan Misinformasi Masif: AI generatif mampu menciptakan teks, gambar, dan video deepfake yang sangat realistis dalam skala besar. Tanpa regulasi yang mewajibkan transparansi (misalnya, pelabelan konten hasil AI) dan akuntabilitas, penyebaran hoaks dan propaganda akan semakin mudah serta sulit dibendung, berpotensi memecah belah opini publik dan memicu konflik sosial yang serius.
-
Bias dan Diskriminasi Algoritma: Jika sistem AI dikembangkan tanpa pedoman etika dan pengawasan ketat, ada risiko besar AI akan memperparah bias yang sudah ada dalam data pelatihannya. Hal ini dapat mengarah pada diskriminasi di berbagai area penting seperti rekrutmen tenaga kerja, penegakan hukum, atau layanan publik, sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap teknologi AI.
-
Pelanggaran Privasi dan Keamanan Data: Pengembangan AI membutuhkan data dalam jumlah besar. Tanpa regulasi yang kuat mengenai pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data (terutama data pribadi), risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data akan sangat tinggi, mengancam hak-hak individu serta perlindungan data pribadi secara fundamental.
Mencegah “Telat Mikir” Berulang: Jalan ke Depan

Perpres AI, meskipun penting sebagai langkah awal, harus menjadi instrumen yang tepat dan adaptif. Pemerintah mungkin memiliki beragam pertimbangan untuk menempuh jalan ini alih-alih menunggu Undang-Undang AI yang spesifik, namun hal tersebut tidak membenarkan potensi ketidakcukupan substansi hukum secara jangka panjang. Oleh karena itu, yang terpenting adalah Perpres AI ini harus melalui mekanisme uji publik yang proper dan transparan, guna menghindari kegaduhan atau bahkan kegagalan setelah kebijakan tersebut diterbitkan.
Berikut adalah beberapa pelajaran krusial yang bisa kita tarik dari pengalaman masa lalu untuk merumuskan regulasi AI yang efektif:
-
Regulasi Inklusif dan Kolaboratif: Jangan biarkan regulasi disusun hanya dari “menara gading.” Libatkan semua pemangku kepentingan—akademisi, praktisi industri AI (terutama mereka yang berada di garis depan), masyarakat sipil, hingga pakar etika—sejak awal perumusan. Pemahaman multi-perspektif akan menghasilkan regulasi AI yang lebih adaptif, relevan, dan berkelanjutan.
-
Fokus pada Prinsip Universal, Bukan Hanya Teknologi Spesifik: Teknologi AI akan terus berkembang dan berubah dengan cepat. Oleh karena itu, regulasi AI harus berpegang pada prinsip-prinsip etika AI universal seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, keamanan, dan perlindungan privasi. Pendekatan ini akan membuat regulasi tetap relevan terlepas dari perkembangan teknologi AI di masa depan.
-
Membangun Fondasi yang Mendukung Inovasi: Regulasi tidak boleh menjadi rem, melainkan fondasi yang kokoh untuk pengembangan AI yang bertanggung jawab. Ini berarti perlu ada ruang bagi eksperimen, regulatory sandbox, dan dukungan nyata bagi riset AI agar inovasi lokal dapat tumbuh dan bersaing secara global.
-
Antisipasi Celah Hukum: Belajar dari pengalaman UU 36/1999 yang tidak menyebut internet, regulasi AI harus secara aktif mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi celah hukum yang mungkin muncul dari teknologi baru, terutama terkait data, hak cipta konten yang dihasilkan AI, dan otonomi sistem AI.
Era AI adalah revolusi yang tak terhindarkan dan akan membentuk masa depan. Pertanyaan kunci bukanlah apakah kita akan mengadopsinya, tetapi bagaimana kita mengadopsinya dengan bijak. Jika kita gagal belajar dari pengalaman masa lalu, risiko “telat mikir” akan kembali menghantui, menghambat inovasi, dan membuang peluang emas yang terhampar di depan mata. Saatnya bergerak cepat, cerdas, dan bijak dalam merumuskan kebijakan AI demi masa depan Indonesia yang lebih baik.