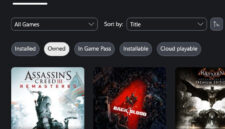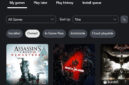Rintik hujan terakhir baru saja berhenti menari di langit Sintra. Butiran air masih bergelayutan manja dari mulut gargoyle batu dan tepian jendela menara Palácio Nacional da Pena. Istana itu berdiri, megah dan misterius, bagaikan sepenggal mimpi yang belum sepenuhnya terungkap. Sejenak, saya terdiam di pelataran, mengarahkan pandangan ke bawah—ke arah kabut yang perlahan sirna, memperlihatkan atap-atap merah tanah dan pucuk-pucuk pinus yang kini kembali menghijau.
Petualangan hari ini belum usai. Meski langit mulai meredup, kaki saya masih menyimpan energi untuk menelusuri kisah lain di jantung kota. Saya beranjak meninggalkan Pena, kembali menuju halte bus hop-on hop-off nomor 434. Bus yang pagi tadi membawa saya mendaki ke puncak negeri dongeng itu, kini mengantar saya turun—menuju realita yang tak kalah memukau, menuju Vila Sintra.
Bus berayun lembut menyusuri jalanan sempit dan berkelok, bersisian dengan mobil-mobil kecil dan pepohonan liar yang mencuat dari tebing. Di balik kaca jendela yang mulai berembun, saya menyaksikan sisa-sisa embun menari di atas rerumputan, dan rumah-rumah mungil yang tampak bagai sketsa arsitek yang terlalu romantis untuk era modern ini. Sintra, dalam segala keunikan dan keindahannya, terasa seperti sebait puisi yang lahir dari imajinasi seorang raja yang terlampau hanyut dalam dunia dongeng.
Beberapa saat kemudian, bus berhenti di halte dekat pusat Vila Sintra. Saya turun, bergabung dengan para turis lain yang menggenggam payung, kamera, dan kantong-kantong belanja kecil berisi cokelat lokal atau magnet kulkas. Udara terasa lebih hangat di sini. Pohon-pohon palem berdiri dengan anggun di tepi jalan, dan di hadapan saya, dinding hotel berwarna pastel menyambut dengan ketenangan: Sintra Boutique Hotel. Di sebelahnya, sebuah toko berwarna hijau terang dengan papan-papan promosi yang menyala menawarkan tur, peta, dan suvenir.
Saya melangkah melewati jembatan batu kecil—tua dan berlumut, dengan relief lambang bangsawan yang seolah telah menyaksikan ribuan langkah kaki melintas, dari sandal sederhana hingga sepatu hiking modern. Tepat di sisinya, sebuah air mancur bundar yang mungil berdiri anggun di bawah tembok batu. Airnya memancar lembut dari ceruk sederhana—menghasilkan suara yang begitu halus, seperti bisikan dari masa lalu.
Tak jauh dari sana, sekelompok pengunjung berkerumun di seberang jalan. Saya mendekat dan tersenyum geli saat melihat seekor sapi hitam-putih dari plastik berdiri tegak di trotoar. Ia mengenakan topi dan syal—maskot toko ALE-HOP, yang menjual berbagai barang lucu dan praktis. Keberadaan seekor sapi di tengah Sintra, entah mengapa, terasa tidak janggal. Kota ini memang selalu menyembunyikan kejutan-kejutan kecil, seperti teka-teki dalam buku cerita anak.
Dari arah kanan, sayup-sayup terdengar dentingan garpu dan tawa riang. Sebuah kafe di bawah pohon yang meranggas seolah memanggil, kursi-kursi putihnya tersusun menghadap jalan, menawarkan istirahat dan cerita. Namun, saya terus melangkah, menanjak sedikit menuju bagian kota yang lebih tua.
Langkah kaki menuntun saya menuju sebuah pelataran batu yang luas, dikelilingi oleh bangunan-bangunan bergaya kolonial yang tampak berdandan rapi menyambut senja. Inilah jantung Vila Sintra—Largo Rainha Dona Amélia, tempat di mana waktu seolah memperlambat detaknya, hanya untuk memberikan kesempatan kepada para pengunjung untuk menikmati seluruh keajaiban yang berserakan.
Dan di sinilah ia berdiri, Palácio Nacional de Sintra—sebuah istana yang tidak menjulang tinggi seperti Pena, melainkan berpadu dengan megahnya di tengah kota, menyatu dengan tanah dan sejarah. Dua cerobong asap raksasa menjulang dari atapnya, berbentuk kerucut putih bagaikan piala es krim raksasa yang terbalik. Pemandangan ini sangat kontras dengan langit yang mulai berwarna jingga, dan ubin-ubin merah yang menghiasi atap bangunan-bangunan lainnya.
Saya berdiri di tengah pelataran, membiarkan mata saya menjelajahi jendela-jendela kecil berbingkai kayu, balkon-balkon batu yang menyimpan jejak waktu, dan pintu masuk besar dengan penjaga museum yang bersandar santai. Di belakang saya, tugu batu pelourinho—tiang keadilan dari zaman kerajaan—berdiri membisu, menyaksikan dunia berubah dari abad ke abad, dari raja-raja hingga rombongan wisatawan dengan swafoto di tangan.
Di sisi kiri, sebuah restoran menawarkan menu makan siang dengan papan tulis besar: “Menu 8 – Bacalhau, Sopa, Sobremesa.” Aroma ikan asin yang ditumis dengan bawang dan minyak zaitun menyeruak dari dapur terbuka. Di sisi kanan, sepasang lansia duduk tenang di bangku, berbagi sepotong pastel de nata, dengan hembusan napas pelan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah lama menghabiskan waktu bersama.
Saya beranjak menuju sisi jalan yang lebih sempit, di mana gang-gang batu mengantarkan saya ke sebuah toko anggur kecil bertuliskan “Loja do Vinho”, tepat di bawah kantor pariwisata resmi Sintra. Seorang pria paruh baya menyapa dari dalam toko, menawarkan cicipan Port manis dan olivas asin. Namun, saya menolak dengan senyuman, tidak ingin waktu berlalu terlalu cepat. Hari telah beranjak ke pukul setengah lima, dan saya tahu matahari tak lama lagi akan bersembunyi di balik bukit.
Palácio Nacional de Sintra bukan hanya sekadar ikon visual dari pusat kota; ia juga merupakan penanda sejarah yang panjang dan berlapis. Istana ini telah berdiri sejak era kekuasaan bangsa Moor, dan setelah penaklukan Portugis, bangunan ini berkembang menjadi kediaman musim panas keluarga kerajaan. Arsitekturnya mencerminkan perpaduan gaya Gothic, Manueline, dan Moorish, yang terus ditambahkan seiring waktu oleh raja-raja yang berbeda. Dua cerobong asap raksasa yang menjulang itu, selain menjadi penanda unik dari kejauhan, merupakan bagian dari dapur kerajaan abad ke-14—saksi bisu perjamuan-perjamuan besar dan ritus istana yang pernah menggetarkan Sintra.
Selama berabad-abad, istana ini bukan sekadar tempat tinggal bangsawan, tetapi juga pusat pengambilan keputusan penting, tempat perlindungan dari wabah di Lisbon, dan bahkan tempat bersembunyi bagi Raja João I saat menghadapi krisis dinasti. Kini, meskipun telah menjadi museum, setiap ruangannya masih membawa gema masa lalu: ubin azulejo dari abad ke-15, langit-langit ukiran dengan burung-burung eksotis, dan lorong-lorong yang menyimpan bisik-bisik sejarah dalam keheningan.
Melangkah ke sisi lain Rua Gil Vicente, saya menemukan satu lagi persimpangan cerita. Deretan kafe dan restoran berjejer dengan bangku putih dan taplak meja bermotif merah. Di antara mereka, sebuah bangunan berwarna biru langit menarik perhatian—Café Paris, nama yang menjanjikan romantisme dari benua lain, namun tetap terasa akrab dalam keramaian Sintra.
Orang-orang menikmati makan siang yang terlambat, menyesap anggur dan espresso, sesekali tertawa atau menatap peta dengan ekspresi bingung. Saya melangkah perlahan, menyusuri lorong-lorong sempit yang terasa lebih tenang, hingga akhirnya tiba di sebuah bangunan yang berbeda dari yang lain.
Tinggi, modern, dan berani, dengan fasad kaca dan tulisan besar—NewsMuseum.
Bangunan modern ini berdiri seolah mengisyaratkan bahwa di antara semua dongeng, harus ada tempat untuk fakta. Kaca-kaca tingginya memantulkan langit yang perlahan berubah warna—dari abu-abu terang menjadi keemasan, lalu perlahan ditelan oleh biru tua. Di dinding sampingnya, terpampang potret-potret besar wajah-wajah bersejarah: wartawan, penyiar, dan kadang tokoh politik, seakan semuanya menatap lurus ke masa depan yang terus bergerak.
Namun, saya tidak masuk. Waktu telah melewati pukul 16.30, dan museum sudah bersiap menutup pintunya. Namun, berdiri di depannya saja sudah cukup untuk menyadari bahwa tempat ini bukan sekadar ruang pamer, melainkan sebuah arsip hidup—tentang bagaimana dunia memberitakan dirinya sendiri. Tentang propaganda, perang informasi, dan kebenaran yang kadang dikemas dalam berbagai bentuk.
Dari sudut pandang tertentu, gedung ini tampak menyatu dengan bangunan sekitarnya, tetapi jendelanya—yang panjang dan terbuka—menghadap langsung ke dunia, ke zaman. Sebuah metafora yang terlalu jelas untuk diabaikan.
Tak jauh dari museum, seorang anak kecil berlari-lari di atas trotoar berbatu, mengejar burung merpati yang bertengger di atap rumah toko. Ibunya memanggil pelan, sementara seorang lelaki—mungkin ayahnya—memotret dari sisi lain. Di bawah lampu jalan yang mulai menyala satu per satu, kota ini tampak melambat, seolah menanti malam dengan segenap kesabaran yang dimiliki orang tua.
Saya menoleh ke belakang sekali lagi. Palácio Nacional de Sintra masih berdiri, putih dan kokoh, dengan cerobong-cerobong yang kini tidak lagi memantulkan cahaya, melainkan menampung sisa warna jingga yang jatuh perlahan di permukaannya. Tidak banyak orang tersisa di pelataran, hanya beberapa siluet turis yang terburu-buru, dan seorang pengamen tua yang mulai mengemasi gitar dan topinya.
Dunia terasa melunak.
Dan di antara semua langkah yang saya tempuh hari ini—dari kabut Pena yang agung hingga gemerlap lampu Vila yang sederhana—saya merasa seperti baru saja menyusun satu babak utuh dalam novel yang belum selesai. Mungkin bukan akhir, tetapi semacam titik koma: tempat bernapas sejenak sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya.
Epilog: Tentang Dua Bangunan dan Dua Waktu
Ada sesuatu yang khas dari dua bangunan yang menjadi penanda hari ini—Palácio Nacional da Pena, yang tinggi dan menjulang, mewakili masa lalu yang dibayangkan; dan NewsMuseum, yang datar dan terbuka, melambangkan masa kini yang terus disusun. Di antara keduanya, saya berjalan. Kita berjalan.
Sintra, pada akhirnya, bukan sekadar kota yang penuh istana. Ia adalah mozaik dari waktu—yang mengizinkan dongeng dan berita hidup berdampingan, tanpa saling meniadakan. Dan dalam senja yang hampir usai ini, saya tahu, ada bagian dari diri saya yang ingin tinggal lebih lama, duduk di salah satu bangku itu, menulis ulang dunia dari sudut pandang yang berbeda.
Tapi waktu terus bergerak. Dan bus berikutnya telah menunggu.