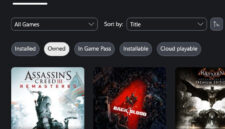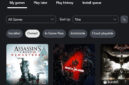Madura, pulau di Jawa Timur, pada mulanya dikenal lewat karapan sapi, olahan daging yang dibuat sate, atau tempat pangkas rambut yang popularitasnya menyaingi Garut. Tapi, Madura tidak hanya itu. Apa pun yang berhubungan dengan besi, bahkan yang berujung kriminal, kerap pula dilekatkan kepada penduduk asal pulau tersebut. Sayangnya, sebagaimana sebuah stereotipe pada umumnya, narasi ini bermasalah.
Muhammad Sholehuddin baru saja mengirimkan besi bekas yang ia kumpulkan kepada pengepul langganan ketika BBC News Indonesia bertemu dengannya pada satu siang yang cukup terik di Pamekasan, Madura, akhir Juni silam.
Walaupun usianya sudah menginjak kepala lima, tangannya masih cekatan memilih dan memilah tumpukan besi di hadapannya. Besi mana yang sekiranya laku dijual, besi mana yang tidak.
Mengenakan singlet dan topi berwarna merah, Sholehuddin menuturkan perkenalannya dengan pencarian besi dimulai pada 1998 atau lebih dari 25 tahun.
Keputusan Sholehuddin mencari besi bekas didorong faktor pemenuhan kebutuhan hidup. Pilihan yang tersedia untuknya tidak kelewat banyak, dan besi, pada akhirnya, memberikan peluang—walaupun terbatas—kepadanya.
Sama seperti pekerjaan di sektor informal lainnya, mengumpulkan besi tidak pernah pasti.
“[Dapatnya] tidak tentu. Kadang sampai 50 kilogram, kadang 20 kilogram, kadang 10 kilogram,” tuturnya menanggapi BBC News Indonesia.
Proses mencari besi, Sholehuddin mengaku, tidak selalu mudah. Ia harus menyortir di antara barang-barang rongsok lain yang jumlahnya tidak sedikit. Tak selalu ia memperoleh besi yang diharapkan.
“Lebih enak menjualnya [besi]. Mencarinya agak sulit,” ungkapnya.
Kepala Sholehuddin kian pusing manakala harga besi bekas tengah mengalami penurunan. Beberapa bulan lalu, satu kilogram besi dihargai Rp6.000. Kini, nilainya turun cukup signifikan: Rp4.000 per satu kilogram.
Kalau sedang bagus-bagusnya, Sholehuddin mampu membawa pulang Rp100.000 dalam satu hari. Sebaliknya, jika kurang kondusif, mengantongi Rp50.000 saja sudah dianggap ‘untung’—daripada tidak sama sekali alias nol rupiah.
“Belum lagi kalau hujan. Itu juga bikin susah,” imbuhnya.
Namun, Sholehuddin menolak tunduk. Meski kenyataan sering kali tidak berpihak padanya, ia akan tetap meneruskan pekerjaan mencari dan menjual besi bekas.
Ia menyimpan satu angan-angan yang masih ingin diwujudkan: membangun tempat pengepulannya sendiri.
“Tidak bisa [membangun] karena dari dulu kurang modal,” katanya.
Selama ini, besi yang ia peroleh disimpan di rumah sebelum dibawa ke pengepul. Alhasil, kondisi di rumahnya tidak ideal sebab harus berbagi ruang antara satu dan yang lainnya.
Sholehuddin tidak ingin terus-menerus memanggul beban seperti itu.
Oleh karenanya, ketika terdapat pandangan yang menyatakan orang Madura menghalalkan segala cara dalam mencari besi, termasuk mencuri, Sholehuddin tidak terima.
“Saya tidak mau [mencari] besi curian,” tegasnya. “Kami bekerja yang penting lurus [tidak berbuat jahat].”
Bagaimana stereotipe orang Madura dan pencurian besi terbentuk?
Salah satunya melalui distribusi informasi di media.
Pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian besi yang dilakukan orang Madura tersebar di berbagai kanal, dalam waktu relatif lama—sejak belasan tahun lalu.
Pada 2009, terdapat satu berita yang memuat kejadian pencurian besi di Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura), Jawa Timur. Pelaku, menurut keterangan polisi, berasal dari Bangkalan, Madura.
Ia diduga membawa tiga ton besi berjenis stainless untuk nantinya dijual ke Surabaya. Pelaku membantah kalau telah mencuri besi seraya menyatakan bahwa ia membelinya dari nelayan di daerah tersebut.
“Saya pikir besi itu limbah proyek,” ucapnya.
Lalu pada 2017, dua warga Sumenep, Madura, ditahan polisi lantaran mencuri besi dari toko bangunan. Keduanya beraksi malam hari. Satu pelaku masuk ke lokasi dengan memanjat tembok, satunya berjaga-jaga di luar.
Lima tahun ke depan, 2022, dua warga asal Sampang, Madura, ditangkap setelah kepergok mencuri besi cor di salah satu pondok pesantren. Penangkapan ini bermula dari kecurigaan warga yang melihat besi untuk pembangunan asrama sering hilang.
Setahun berselang, 2023, pejabat di Kementerian Perhubungan mengatakan upaya penghidupan kembali (reaktivasi) jalur kereta api di Madura terkendala, satu di antaranya, proporsi rel besi yang diperkirakan cuma tersisa di bawah 30%.
Rel besi di Madura diduga hilang untuk diperdagangkan.
Di Bali, pada 2025, warga Madura diringkus polisi usai menggondol ratusan besi—tepatnya dalam 51 ikat—yang diambil dari pembangunan sebuah vila. Pelaku mengaku berencana menjual besi-besi itu untuk memenuhi keperluan hidup.
Aksi komplotan pencuri besi digagalkan pihak berwenang di Gresik, Jawa Timur, 2022 lalu. Salah satu anggotanya adalah warga Sampang, Madura. Para pelaku menyasar besi sepanjang 54 meter pada pembangunan jalan desa. Kerugian ditaksir menyentuh Rp13,5 juta.
Rentetan peristiwa tersebut lalu dijadikan ‘inspirasi’ serta diamplifikasi oleh konten-konten populer di media sosial seperti YouTube.
Ambil contoh sebuah konten berisikan seorang komedian ternama asal Madura yang menyajikan cerita ihwal hubungan orang Madura dan besi dengan bungkus komedi atau satir.
Konten itu dipublikasikan tiga tahun lalu dan telah ditonton lebih dari 40.000 kali.
Konten dengan nuansa serupa muncul kembali pada 2023, kali ini mengambil format podcast. Bahasannya, lagi-lagi, Madura dan besi. Sejak diunggah, konten bersangkutan mengumpulkan 270.000-an views.
Perbincangan mengenai orang Madura dan hubungannya dengan besi tidak seketika lenyap. Di media sosial X dan TikTok, misalnya, banyak akun mengeluarkan candaan soal itu.
Biasanya, konten-konten yang menyinggung Madura dan besi, panen engagement.
Satu konten di TikTok mempertontonkan interaksi content creator dengan pengikutnya, membahas perkara besi.
Salah satu pertanyaan yang dilontarkan dalam interaksi pada konten itu: “Kang, apakah orang Madura kalau masuk surga pintunya bakal dikilokan—dijual?”
Konten tersebut cukup viral dan disukai ratusan ribu akun. Di kolom komentar, ramai bermunculan reaksi atas unggahan itu. Mereka, rata-rata, memberikan balasan tak jauh berbeda: bernada lelucon.
Sementara di video lainnya, content creator bertanya kepada anak muda Madura soal hal yang tidak disukai dari pandangan publik terhadap masyarakat Madura.
Selama kamu kuliah di Jember, stereotip orang Madura masih ada?
Wah, masih banget.
Jadi, apa yang kamu tidak suka?
Orang Madura suka mengambil besi, seperti di rel kereta. Itu aku enggak suka, walaupun belum pernah melihat.
Belum pernah melihat tapi melakukannya?
Enggak, dong.
Konten ini mendulang puluhan ribu likes.
Tidak semua konten tentang Madura dan besi menggambarkan kesan ‘ramah’ yang mengundang tawa. Ada pula yang cenderung menyimpulkan tanpa disertai bukti yang jelas.
Satu unggahan pada Mei 2025 berisi berita mengenai pencurian ratusan besi di konstruksi tol dekat Jakarta International Stadium (JIS). Tidak sedikit komentar dari warganet yang menuduh orang Madura melakukan tindak pidana ini.
Setiap ada pencurian besi, tudingan kepada orang Madura sebagai pihak di belakangnya begitu mudah dilontarkan. Di sinilah prasangka subjektif dapat berbahaya, ujar pengajar sosiologi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Bernando J. Sujibto.
“Kalau kita ngomongin soal dampak dan efeknya, besar sekali,” ucapnya saat diwawancarai BBC News Indonesia, Juni kemarin.
“Akan ada penyangkalan, penolakan besar-besaran, terhadap kelompok yang dilabeli ini sebab masyarakat sudah menganggapnya sebagai kebenaran,” tambahnya.
Mengapa muncul stereotipe orang Madura dan pencurian besi?
Bernando mengungkapkan ada banyak faktor yang mendorong stereotipe itu muncul.
Secara umum, menurutnya, publik harus bisa membedakan mana tindakan yang dilakukan secara personal, mana yang dilakukan secara komunitas etnis.
“Maksudnya begini, kita sebagai masyarakat itu tidak bisa serta-merta mengidentifikasi satu bentuk [aksi] kriminal, [satu] kegiatan personal, itu langsung otomatis menjadi identitas etnis,” tuturnya.
“Itu pertama yang harus diperhatikan. Artinya, kita secara sosiologis harus mampu, masyarakat multikultural harus mampu, untuk menempatkan itu.”
Kasus pencurian besi marak terjadi, dan pelakunya tidak berasal dari satu kelompok etnis saja. Dengan kata lain: tindak pelanggaran ini dapat dilakukan siapapun.
Pada Februari 2025, pria asal Bojonegoro terpaksa berurusan dengan polisi selepas mencuri besi dari rel kereta api. Tersangka pencurian membawa kabur sekitar puluhan besi yang difungsikan menjadi penahan batu dan konstruksi tanah rel.
Saat aksi pencurian tiga ton besi di Jembatan Suramadu, pelaku—dari Madura—tidak beraksi sendirian. Ia ditemani warga Mojokerto yang berperan mengangkut besi dengan truk. Ia dibayar Rp400 ribu.
Di Bandung, Jawa Barat, polisi meringkus tiga warga Kabupaten Bandung Barat lantaran mencuri besi rel cadangan kereta api. Sekitar 38 batang besi—yang sudah terpotong—menjadi barang bukti. Besi-besi ini, rencananya, akan dijual. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengatakan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp513 juta.
Bernando menjelaskan apabila mengamati representasi Madura secara keseluruhan, dapat dilihat betapa “yang berkaitan dengan besi itu mungkin tidak sampai 10%,” tandasnya.
“Memang di Madura itu banyak ciri khas. Salah satunya berdagang besi atau keberadaan toko besi. Dan itu, kalau saya melihatnya, saat bicara dalam konteks perantauan, sedikit jika dibandingkan dengan yang lain, seperti toko kelontong, sate, atau cukur rambut,” terangnya.
Pengaruh informasi dan media tidak bisa dimungkiri berperan dalam membingkai sekaligus menancapkan stereotip orang Madura dekat dengan besi—sampai yang negatif sekalipun.
Sebelum era media sosial berkembang, Bernando menerangkan, “terdapat banyak sekali orang-orang membuat parodi, humor, dan sejenisnya mengenai stereotip komunitas etnis tertentu.”
Madura bukan pengecualian.
Seiring waktu, narasi mengenai kelompok etnis tertentu terus berkembang dan direproduksi melalui media sosial dalam format yang kurang lebih mirip sebelum media sosial itu meledak: lelucon, sketsa, atau satir.
“Secara materi, mungkin, tidak ada upaya untuk meninggalkan label terhadap kelompok etnis tertentu. Tapi, penerimaan ke audiens bisa jadi berbeda,” tambah Bernando.
“Makanya, sebagai pembuat konten, prinsip kehati-hatian itu sebaiknya dijaga betul. Apalagi sekarang era media sosial dengan banyak intensi dan kepentingan.”
Media sosial, imbuh Bernando, berperan krusial dalam “reproduksi stereotip.” Pasalnya, aliran informasi di sana tidak dapat dibendung dan, pada satu titik, akan memengaruhi cara pikir publik ketika melihat suatu kasus.
Kenyataan di Indonesia, Bernando melanjutkan, dibangun berdasarkan eksistensi kelompok etnis yang jumlahnya sangat banyak. Sebagai kelompok etnis, mereka memiliki identitas etnisnya masing-masing.
Namun, “yang berkembang dan sangat umum di kita adalah bagian yang stereotip ini,” Bernando berkata. Unsur stigma yang disertakan kepada komunitas etnis tertentu lebih menonjol, terkenal, dan terinternalisasi secara kuat di kelompok masyarakat yang lain sebagai fakta.
“Ini menjadi satu cara pandang yang relatif agak berisiko di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Ketika ada isu pencurian besi, orang Madura yang dituduh. Ini yang mesti diluruskan,” ujarnya.
“Saya mempertegas bahwa kesadaran kita, pengetahuan kita terhadap satu kasus, apa pun yang dilakukan oleh siapapun, itu cara pandangnya tidak langsung dilabelkan kepada satu komunitasnya.”
Ongkos yang harus dibayar jika stereotip ini masih dipertahankan dan dirawat tidaklah murah. Masyarakat Indonesia yang punya latarbelakang bermacam rupa rentan digesek dengan isu etnis—dan kian mengerikan kala sudah digabungkan bersama agama.
Dari sisi kelompok yang terstigmatisasi, pertaruhan mengenai akses terhadap pemenuhan atas hak berpeluang terjadi. Sebab komunitasnya dianggap identik dengan suatu tindak kejahatan, misalnya, mereka bisa jadi tidak memperoleh pelayanan yang adil dari pemerintah—atau unsur lainnya.
Dalam kasus stereotip besi, Bernando belum melihat kecenderungan ‘penyingkiran’ dan ‘pengabaian’ terhadap akses dialami orang-orang Madura. Tapi, Bernando menegaskan, “risikonya tetap terbuka lebar.”
“Eksklusi seperti ini tidak bagus sebenarnya, menjadi preseden buruk dalam konteks kita hidup bermasyarakat. Karena pembacaan yang diterapkan adalah berdasarkan identitas kelompok,” tambahnya.
Bernando berpendapat negara—pemerintah—juga punya kontribusi atas terjadinya pemberian stereotip kepada masyarakat Madura—atau kelompok etnis lainnya.
Pasalnya, pemerintah sering kali baru aktif ‘turun’ ketika ada konflik. Sebelum itu, pemerintah dipandang Bernando tidak memiliki komitmen serius dalam mengurai masalah stereotip.
Indikatornya yakni, Bernando menyatakan, sedikitnya ruang bertemu antarmasyarakat, baik itu di tingkat pendidikan maupun di level publik. Bentuk pertemuan tersebut ialah diskusi, acara budaya, hingga kegiatan-kegiatan nonformal yang diselenggarakan di ruang publik—taman, alun-alun, dan seterusnya.
Ketika ruang yang diharapkan itu tidak tercipta, maka kelompok-kelompok masyarakat—dengan etnis berbeda-beda—tidak bisa bertemu dan berinteraksi. Konsekuensinya, mereka tidak dapat mengenal satu sama lain dan saat muncul prasangka, yang terjadi berikutnya adalah ‘pembenaran’—bahwa kelompok etnis A, seperti contoh, memang sering melakukan aksi kriminal.
Dukungan sosial yang tak maksimal mendorong ketidakmampuan masyarakat untuk mengenal kelompok etnis lainnya, dan pemerintah punya andil di situ, sebut Bernando. Sehingga, bukannya inklusif, Bernando menegaskan, realitas sosial malah justru “semakin eksklusif.”
“Jadinya gambaran kehidupan masyarakat multikultural yang menjunjung perbedaan, pluralitas, itu seperti cerita fiktif,” pungkas Bernando.
Apa akar masalahnya?
Mohammad Fakkar, 56 tahun, terdorong berdagang besi tua setelah melihat teman-teman di kampung halamannya, Pamekasan, Madura, yang lebih dulu sukses berbisnis di bidang ini.
Pada 2006, ia memutuskan balik merantau dari Surabaya dan mulai membangun usaha pengumpulan dan penjualan besi bekas.
“Jadi, saya coba-coba untuk berdagang [besi] kecil-kecilan. Saya mengumpulkannya di rumah dan menjualnya di sekitar Pamekasan,” ceritanya.
Besi tua—bekas—dipilih sebab “sangat mudah mencarinya,” terang Fakkar sekaligus menggambarkan faktor apa yang memicu kedekatan orang-orang Madura dengan usaha jual-beli besi.
“Besi tua ada di rumah-rumah warga, di bengkel-bengkel motor atau mobil. Bagi mereka, besi tua yang tidak diapa-apakan lagi, bisa kami jual dan [kami] dapat uang”.
“Seperti motor rusak itu, contohnya, biasanya dibuang sama orang. Kami bawa saja akhirnya. Atau besi-besi berkarat di rumah warga yang tidak terpakai,” Fakkar menjelaskan panjang-lebar.
Fakkar tak membatasi besi yang ia perjualbelikan. Baik yang sudah berkarat atau tidak, ia dengan tangan terbuka menerimanya.
“Kalau tidak karatan, asalkan [berbentuk] potongan-potongan itu tidak apa-apa. Misalnya, potongan besi dari orang bikin gudang. Itu potongan besinya sudah tidak diperlukan lagi,” ungkapnya.
Alur perdagangan besi tua tidak kelewat rumit.
Para pengepul, seperti Fakkar, menerima besi tua dari para pengumpul—bisa perorangan atau kelompok. Satu kilogram besi dihargai Rp4.000, angka yang sudah menurun dibanding sebelumnya: Rp6.000.
Setelah di tangan pengepul, besi tua lalu disalurkan ke sejumlah titik di kawasan industri di sekitar Surabaya, Gresik, Mojokerto, sampai Sidoarjo. Di daerah tersebut, berdiri banyak pabrik pengolahan besi.
Dalam seminggu, Fakkar dapat mengumpulkan belasan ton besi tua. Dari jumlah tersebut, sebanyak dua sampai tiga ton dijual kembali.
Keuntungan yang ia peroleh tidak pasti, tergantung harga besi per kilogram. Tapi, dulu, Fakkar memberi gambaran, ia dapat mengumpulkan sampai Rp100 juta lebih—dengan perhitungan jika besi tua yang dijual di atas 10 ton.
Harga besi, menurut Fakkar, ditentukan tebal atau tidaknya besi tersebut. Semakin tebal besinya, harganya kemungkinan akan tinggi. Kalau tipis, harganya pun mengikuti: lebih rendah.
Sementara Subaidi, pengepul berusia 35 tahun, menjelaskan besi tua dibagi berdasarkan grade—kelas. Ada grade ‘A’ yang berarti besinya mahal. Ada grade ‘B’ dan ‘C’ yang dipatok dengan harga sedang serta rendah.
“Besi-besi dari gudang itu mahal, biasanya. Kalau yang murah itu seperti besi dari sepeda onthel,” katanya.
Subaidi baru tiga tahun berkecimpung di usaha besi tua. Ia meneruskan bisnis orang tuanya yang telah dirintis satu dekade terakhir.
Dalam sebulan, ia mampu menjual besi tua ke pabrik-pabrik di sekitar Jawa Timur sebanyak dua kali. Jumlahnya menyentuh delapan ton, dengan keuntungan yang dibawa pulang sebesar Rp40 juta.
Kini, Subaidi tengah lumayan pening sebab harga besi belum kembali ke level yang menguntungkan. Satu kilogram besi tua ditetapkan Rp4.000—turun dari Rp6.000—dan itu cukup memengaruhi neraca keuangannya.
Keputusan warga Madura untuk menjalankan usaha perdagangan besi tidak sekonyong-konyong muncul. Terdapat konteks yang membentuk struktur ekonomi Madura saat ini, dan sedikit-banyak menjelaskan mengapa sektor informal yang mendominasi.
Karakter tanah di Madura, tulis Kuntowijoyo melalui bukunya yang berjudul Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940 (2002), berbeda dengan di Jawa sehingga ekosistem yang lahir pun turut memberi efek terhadap pola hidup masyarakatnya.
Permukaan tanah di Madura, mengutip Kuntowijoyo, didominasi susunan batu dan endapan kapur dengan lapisan aluvial (yang menentukan tingkat kesuburan) di sepanjang area pantai utara, di samping tersebar pula di sebagian kecil wilayah daratan seperti Pamekasan atau Bangkalan.
Dengan begitu, hanya kaktus dan palem yang mampu tumbuh dan berkembang secara baik. Tanaman lain seperti jagung memang dapat ditanam selama akarnya menerobos jauh lapisan yang ada serta mengandalkan pasokan air bawah tanah.
Madura, di waktu bersamaan, kekurangan tanah vulkanis. Maka dari itu, usaha pertanian hanya bisa dilakukan di tempat-tempat dengan kandungan aluvial yang cukup.
Cuaca menjadi elemen yang tidak bisa dikesampingkan, imbuh Kuntowijoyo. Di Madura, musim kemarau berjalan lebih lama sekaligus kering yang kemudian turut berdampak kepada tingkat kelembapan.
Untuk bertahan, warga Madura lalu bersiasat dengan mengandalkan ekologi tegalan, sebuah sistem pertanian di luar yang bertumpu pada ladang dan sawah.
Ekologi tegalan, tulis antropolog Amerika, Clifford Geertz, dalam Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia (1963), punya karakteristik seperti ketergantungan tanaman hidup pada curah hujan, produktivitas varietas rendah kendati jumlahnya banyak, serta risiko gagal panen terbuka lebar.
Musababnya, faktor musim yang tak menentu. Akibatnya, hasil pertanian di Madura cenderung tak proporsional.
Kuntowijoyo mencatat lahan-lahan di Madura berisiko tinggi tidak produktif.
Kondisi yang tidak terlalu ideal ini menjadi tantangan sampai sekarang. Madura dikepung dengan permasalahan ekonomi maupun sumber daya yang kompleks, dan masyarakat di sana harus menghadapinya.
Hasil penilaian dari Pemerintah Provisi (Pemprov) Jawa Timur pada 2024 menempatkan empat wilayah di Madura ke dalam kantong-kantong kemiskinan.
Tiga daerah bahkan duduk di posisi tiga teratas. Ketiganya yaitu Sampang (221.710 jiwa penduduk miskin), Bangkalan (206.100 penduduk miskin), dan Sumenep (196.660 penduduk miskin).
Lalu satu daerah lainnya, Pamekasan, berada di peringkat enam (123,46 ribu orang miskin).
Kelangkaan sumber daya alam—berupa lahan yang tak produktif—mendorong lahirnya moral ekonomi yang berorientasi pada kerja (labour ethics) ketimbang tanah (land ethics), tulis Totok Rochana dalam Orang Madura: Suatu Tinjauan Antropologis (2012).
Berangkat dari perubahan tersebut, orang-orang Madura memutuskan untuk mengolah usaha di luar pertanian—termasuk merantau—demi memperoleh penghidupan yang lebih baik.
Masyarakat Madura berfokus pada apa yang didefinisikan sebagai “rasionalisasi ekonomi,” sebuah etos atau prinsip yang mengedepankan kerja keras guna keluar dari zona kemiskinan.
Di Jakarta, publik akan mudah menjumpai komunitas Madura mengais harapan dengan membuka toko kelontong, berjualan sate, atau menjajakan kopi keliling. Pemandangan serupa dapat ditemukan di kota-kota lainnya.
Di antara itu, jual-beli besi tua turut menyelinap dan (membantu) membukakan pintu ekonomi untuk setiap warga Madura.
Subaidi menampik anggapan orang Madura suka mencuri besi. Ia menegaskan “tidak semua orang Madura seperti itu.”
“Itu enggak benar. Itu enggak benar,” katanya mengulang dua kali.
Senada dengan Subaidi, Fakkar menyebut tidak semua kasus pencurian besi orang Madura yang melakukannya.
“Orang kalau lapar dan tidak punya uang untuk beli nasi, juga tidak punya pekerjaan, pasti mencuri,” imbuhnya.
“Dan itu bisa dilakukan siapa saja. Bukan berarti langsung orang Madura.”
Fakkar berpandangan berjualan besi tua merupakan satu dari sedikit cara orang Madura bertahan di tengah keadaan. Pilihan yang ditawarkan hidup tidak terlampau banyak, dan orang Madura—mau tidak mau, suka tidak suka—harus mengambil jalan yang tersisa.
“Bagi saya, kami orang Madura itu [dilatih dan terlatih untuk] kerja keras,” tegasnya.
Budaya Madura mengenalkan peribahasa berbunyi ‘abantal omba’ asapo’ angen‘ yang berarti “berbantal ombak dan berselimut angin.”
Peribahasa ini punya makna, kerja keras adalah cerminan dari harga diri yang mesti dilakukan dengan sepenuh hati, sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan dan keluarga.
Besi tua, bekas, atau rongsok, alih-alih ditempatkan sebagai sebuah stereotip, sudah saatnya dilihat dalam bingkai kacamata upaya masyarakat Madura memacu roda nasib.
- Ratusan pengungsi eks-Syiah kembali ke Sampang setelah dibaiat menjadi Sunni, Tajul Muluk masih ditolak
- ‘Ditentang warga hingga dianggap gila’ – Perjuangan Slaman ubah lahan bakau kritis di Pesisir Madura jadi ekowisata
- Lonjakan kasus Covid-19 terjadi di Madura, epidemiolog duga jumlah sebenarnya bisa jauh lebih besar
- Tudingan ‘mengalahkan minoritas demi keinginan mayoritas’, di balik pembaiatan dan keinginan pengungsi Syiah Sampang pulang kampung
- Pengungsi Syiah Sampang: Di antara pilihan iman dan harapan pulang
- Baiat pengungsi Syiah menjadi Suni: Cari jalan untuk pulang, namun trauma warga ‘membekas dan ‘tak akan pernah pulih’
- Migrasi tradisional NTT ke ‘rumah kedua’ Malaysia, sejarah ‘tangis dan tawa’ selama puluhan tahun
- Cara anak muda Mentawai menjaga tradisi – ‘Kami bukan orang-orang terbelakang’
- Perempuan pemburu bebunyian — ‘Saya berusaha mewarisi nilai leluhur sekaligus membongkarnya’
- Garis kemiskinan versi Bank Dunia dan pemerintah, mana yang lebih realistis?
- Pemerintah klaim kemiskinan ekstrem akan 0% akhir 2024, tapi di Papua bertahan hidup ‘harus setengah mati‘
- Vasektomi syarat bansos? – ‘Kalau mau berantas kemiskinan, perluas lapangan kerja dan tingkatkan upah’