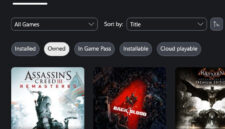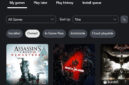Minggu pagi yang cerah (25/5) dikejutkan dengan semburat mendung di langit Tangerang. Langkahku menjejak Stasiun Tangerang setelah turun dari KRL. Suara hiruk pikuk para penumpang dan para penjaja di area luar stasiun merupakan potret keseharian bagi para komuter. Di sinilah, petualangan unikku dimulai. Bukan sekadar *walking tour* biasa, melainkan sebuah ekspedisi sejarah yang digagas Kompasiana dalam tajuk “Ketemu Walking Tour: The Hidden History of Pasar Lama”.
Stasiun Tangerang bukanlah sekadar terminal transportasi. Bangunan bersejarah yang berdiri sejak 2 Januari 1889, warisan era kolonial Belanda, menyimpan segudang kisah. Dahulu, stasiun ini berfungsi vital dalam menunjang aktivitas ekonomi, khususnya pengangkutan hasil bumi dari Tangerang menuju Batavia dan sebaliknya. Dengan struktur atap yang menjulang tinggi dan sisa-sisa lantai tegel bermotif klasik, stasiun ini menjadi saksi bisu ribuan langkah yang telah berlalu.
Elsa Novia Sena, *tour guide* kami yang bersemangat dan juga seorang Content Creator dari Benteng Walking Tour, menyambut kami dengan senyum ramah. Mengenakan kaos merah cerah dan sepatu kets yang nyaman, Elsa mengajak kami mengupas lapisan demi lapisan sejarah yang mungkin selama ini terlewatkan begitu saja.
Sebanyak 25 peserta berpartisipasi dalam Temu Kompasiana kali ini, dibagi menjadi dua kelompok. Aku bersama 15 peserta lainnya memulai perjalanan menuju destinasi pertama yang unik dan membangkitkan rasa ingin tahu: sentra pembuatan kecap Benteng SH atau Siong Hin, yang telah eksis sejak tahun 1920. Saat ini, usaha kecap Benteng SH dikelola oleh generasi keempat.
Selanjutnya, kami beranjak dari pabrik kecap Benteng SH menuju salah satu produsen kecap ternama di Tangerang yang wajib dikunjungi, yaitu Teng Giok Seng. Dari lokasi produksinya, terlihat jelas bahwa pabrik kecap ini memiliki sejarah yang lebih panjang, tepatnya sejak tahun 1882. Awalnya, kecap ini diproduksi oleh Teng Hay Soey, yang kemudian diteruskan oleh Teng Giok Seng. Kini, produk ini lebih dikenal dengan merek kecap Cap Istana.
Mendengarkan penjelasan Elsa, aku tersadar bahwa kecap bukan hanya sekadar bumbu penyedap. Ia adalah saksi bisu perjalanan panjang komunitas Tionghoa Benteng di Tangerang.
Perjalanan berlanjut ke Masjid Jami Kalipasir, salah satu masjid tertua di Tangerang yang sudah berdiri sejak tahun 1576. Masjid ini adalah manifestasi nyata harmoni antarbudaya yang telah terjalin sejak ratusan tahun silam. Di sekeliling masjid, komunitas Tionghoa, Arab, dan pribumi hidup berdampingan secara damai. Bangunannya sederhana dengan atap menara yang menyerupai pagoda. Elsa menjelaskan bahwa di halaman depan terdapat makam para tokoh muslim, bupati, dan juga makam istri Sultan Ageng Tirtayasa.
Tidak jauh dari Masjid Jami Kalipasir, tepat di seberangnya, terdapat Toapekong Air. Terletak di tepi Kali Cisadane, tempat ini merupakan altar terbuka yang digunakan untuk berbagai ritual, termasuk sembahyang leluhur dan peribadatan dewa air, termasuk pelaksanaan ritual Fang Shen, yaitu tradisi melepaskan hewan ke alam bebas. Ikan, burung, bahkan kura-kura sering dilepaskan ke sungai sebagai simbol pembebasan dan karma baik.
Namun, ada momen istimewa yang membuat tempat ini benar-benar hidup: setiap tahun pada hari kelima bulan kelima dalam kalender lunar, atau pada akhir bulan Mei tahun ini, masyarakat Tionghoa Benteng berkumpul di sini untuk merayakan Peh Cun, yang dalam budaya Tionghoa identik dengan lomba perahu naga.
Di sini, Elsa juga menjelaskan asal-usul istilah “Cina Benteng” yang sering kami dengar sejak awal *walking tour*. Menurutnya, sebutan Cina Benteng bukanlah nama resmi, melainkan lebih merupakan istilah sosial yang awalnya digunakan untuk merujuk pada komunitas Tionghoa yang tinggal di sekitar benteng Makassar di tepi Sungai Cisadane. Benteng ini dulunya dibangun oleh Belanda sebagai pos penjagaan, dan lama-kelamaan kawasan di sekitarnya menjadi pemukiman.
Namun, sebutan itu kemudian memiliki makna yang lebih dalam. Ia menggambarkan komunitas Tionghoa peranakan yang sudah menetap sejak abad ke-17, berbaur dengan budaya lokal, berbahasa Melayu, bahkan banyak yang memeluk agama Islam. Mereka bukanlah imigran baru, melainkan bagian dari sejarah yang ikut membentuk Tangerang. Kini, istilah Cina Benteng justru menjadi simbol kebanggaan akan akar budaya yang kuat.
Perjalanan semakin menarik saat kami tiba di Roemboer Tangga Ronggeng. “Roemboer” sendiri merupakan singkatan dari “Roemah Boeroeng”, yaitu tempat burung walet membuat sarang. Sementara “Tangga Ronggeng” merujuk pada tangga yang dulu berada di Sungai Cisadane, tempat para penari Ronggeng menampilkan pertunjukan. Sayangnya, tangga tersebut sudah tidak ada lagi.
Tepat di depan Roemboer Tangga Ronggeng, berdiri rumah penulis buku silat terkenal, Oey Kim Tiang, atau yang lebih dikenal dengan OKT. Lebih dari 100 judul buku silat telah diterjemahkannya dari bahasa Hokkien ke Melayu Pasar. Itulah mengapa ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang mempopulerkan kesusasteraan Melayu Tionghoa, atau yang juga disebut Melayu Betawi.
Tidak jauh dari sana, tepat di ujung jalan, Klenteng Boen Tek Bio berdiri dengan megah dan anggun. Ini adalah klenteng tertua di Tangerang, yang sejak tahun 1684 hingga kini masih aktif digunakan untuk sembahyang dan perayaan hari besar. Aroma dupa menguar, menciptakan suasana yang magis. “Boen Tek Bio” sendiri berasal dari bahasa Hokkian. “Boen” berarti intelektual, “tek” berarti kebajikan, dan “bio” berarti tempat ibadah. Secara keseluruhan, artinya adalah tempat untuk menjadi umat yang penuh kebajikan dan intelektual.
Elsa menjelaskan bahwa Boen Tek Bio bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat sosial dan budaya bagi warga sekitar. Dan saat berkunjung, kami pun berkesempatan menyaksikan pertunjukan gambang kromong dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak.
Setelah berjalan kaki selama hampir tiga jam, kami tiba di Museum Benteng Heritage. Ini mungkin adalah puncak dari seluruh perjalanan hari itu. Bangunan dua lantai yang terawat dengan baik ini berdiri megah di jantung Pasar Lama. Masih mempertahankan arsitektur aslinya, dari luar tampilan bangunan ini terlihat sederhana, tetapi begitu masuk, aku serasa memasuki lorong waktu. Museum ini menyimpan banyak artefak, foto, dan dokumen yang merekam kehidupan komunitas Tionghoa Benteng dari masa ke masa.
Akhirnya, Ketemu *walking tour* hari itu ditutup dengan manis di Kedai Lampion. Sebuah tempat makan bernuansa *vintage* yang terletak tepat di depan Klenteng Boen Tek Bio. Percakapan di meja makan pun mengalir dengan hangat. Kami saling bertukar kesan, tertawa, dan menyadari bahwa perjalanan hari ini lebih dari sekadar jalan kaki. Ini adalah perjalanan pulang, pulang ke akar, ke sejarah, ke rasa ingin tahu yang sering kita abaikan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern.
Dan hari itu, aku pulang membawa lebih dari sekadar foto-foto, tapi juga sepotong rasa hormat dan cinta baru untuk Tangerang, kota yang diam-diam menyimpan sejarah besar dalam langkah-langkah kecilnya.
Video keseruannya dapat disaksikan di instagram @nininrs yess….