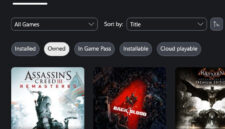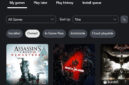14 Agustus, hari kekalahan Jepang (atau 15 Agustus menurut kalender Jepang), menandai berakhirnya Perang Dunia II dan memicu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. 80 tahun berlalu, momen ini kini diperingati sebagai Hari Ianfu Internasional, sebuah penghormatan bagi para perempuan yang menjadi korban perbudakan seksual oleh militer Jepang.
Direkrut dengan janji manis yang palsu atau diculik paksa dari tengah keluarga, para perempuan muda, yang dikenal sebagai “ianfu” atau wanita penghibur, mengalami mimpi buruk di balik dinding-dinding sunyi.
“Nenek saya, Mbah Tugirah, pernah ‘disenangi’ tentara Jepang waktu zaman penjajahan,” ungkap Anik Sukaningsih, generasi ketiga dari penyintas ianfu di Indonesia.
“Dia disiksa, dianiaya. Kalau menolak diperkosa, menolak ‘disenangi’, ya dipukul,” lanjutnya, menggambarkan kengerian yang dialami sang nenek.
Tugirah hanyalah satu dari sekian banyak perempuan yang menjadi korban. Tragisnya, ada di antara mereka yang baru berusia sembilan tahun ketika peristiwa kelam itu terjadi.
“Kami masih kecil, tidak berani. Kalau tidak, mati,” kenang Sri Sukanti, seorang penyintas lainnya, menggambarkan ketidakberdayaan mereka saat itu.
Diperkirakan ratusan ribu perempuan menjadi korban perbudakan seksual atau “ianfu” selama pendudukan Jepang di masa Perang Asia Pasifik, bagian dari Perang Dunia II yang berkecamuk di Asia dan Samudra Pasifik antara tahun 1941 hingga 1945.
Perang Asia Pasifik merupakan konflik antara Jepang melawan negara-negara Sekutu, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan China.
Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, para perempuan ini harus berjuang untuk bertahan hidup, dibayangi stigma dan trauma mendalam.
Berbeda dengan kisah-kisah yang banyak terungkap di Filipina, China, dan Korea Selatan, pengalaman para ianfu di Indonesia masih tersembunyi rapat, terkubur dalam keheningan dan rasa malu yang mendalam.
Selama beberapa generasi setelahnya, kisah pilu perempuan Indonesia yang menjadi budak seks tentara Jepang di Perang Dunia II seolah terkubur dalam ingatan yang memudar.
Didorong oleh rasa ingin tahu, saya mencoba menyelami kembali kisah-kisah ianfu di Indonesia yang kian tergerus oleh waktu.
Inilah kisah tentang gadis-gadis remaja dan perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual oleh militer Jepang selama Perang Dunia II. Mereka dikenal sebagai “ianfu”.
Banyak penyintas ianfu di negara lain telah berani tampil dan berbagi pengalaman pahit mereka. Namun, kisah ianfu di Indonesia justru terpendam, terkubur di balik tabir keheningan selama hampir setengah abad.
Barulah pada awal 1990-an, Tuminah menjadi penyintas ianfu pertama dari Indonesia yang berani membuka suara tentang kekerasan seksual yang dialaminya selama masa pendudukan Jepang.
Keberanian Tuminah ini memicu penyintas lainnya di Indonesia untuk bersaksi tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Jepang.
Kesaksian Tuminah kemudian diterbitkan di harian Suara Merdeka pada tanggal 16 dan 21 Juni 1992. Momentum ini terjadi tak lama setelah Kim Hak Soon, penyintas ianfu dari Korea Selatan, bersaksi di depan publik pada tahun 1991 dan mengajukan gugatan class-action terhadap pemerintah Jepang.
Setelah kemerdekaan, Tuminah menghabiskan hidupnya bersama keluarga dengan berjualan makanan ringan. Ia meninggal dunia pada tahun 2003.
Di makam Tuminah, didirikan sebuah monumen sebagai bentuk penghargaan atas keberaniannya “memecah keheningan”.
“Dia pernah bilang, ‘Nduk, kalau saya [bisa] milih, saya tidak mau menjalani hidup seperti itu, karena itu menyakitkan bagi saya’,” kenang Hening Saptaningsih, keponakan Tuminah, saat ditemui di Solo, Juni lalu.
“Tidak bisa melawan perintah tentara, dan semuanya harus nurut.”
Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, Tuminah tinggal bersama kerabatnya. Ia sempat menikah, namun suaminya meninggal dunia di usia muda. Tuminah kemudian mengadopsi seorang putri.
Sejak kecil, Hening mengenal Tuminah sebagai “Mak Tum”.
“Mak Tum bagi saya adalah sosok perempuan yang sabar, kuat, karena sejak saya kecil Mak Tum ikut bapak saya.”
“Anak yang diadopsi itu umurnya hanya selisih dua atau tiga tahun dari saya. Jadi, saya sering bermain dengan anaknya dan saya diasuh oleh Mak Tum.”
Di sela-sela kebersamaannya dengan “Mak Tum”, Hening ingat betul suatu ketika Tuminah bercerita kepadanya sambil berlinang air mata.
“Dia bercerita, ‘Di hotel itu, di situ berhari-hari aku capek sekali, baik batin maupun fisikku capek sekali’.”
Menurut buku Utang Perang Asia Pasifik, “Ianfu”, Romusha dan Heiho, Tuminah sejak remaja bekerja sebagai pekerja seks komersial yang biasa mangkal di Hotel Slier, yang kini menjadi Kantor Pos Pusat Solo.
Pada tahun 1944, polisi militer Jepang mulai melakukan penangkapan terhadap para pekerja seks di Solo, termasuk Tuminah.
Bersama sejumlah perempuan lain, ia kemudian ditempatkan di ianjo, sebuah bordil khusus untuk melayani tentara Jepang yang berlokasi di Hotel Rusche.
Dalam bahasa Jepang, “ian” berarti perempuan dan “jo” berarti tempat.
“Kami tidak diperbolehkan meminta uang kepada tentara Jepang. Pernah sehari melayani empat laki-laki, tidak dibayar sama sekali,” ungkap Tuminah seperti yang tertulis dalam buku yang diterbitkan pada tahun 2022 itu.
“Maka kalau ora payu (tidak laku), saya lebih senang sebab tetap saja diberi makan.”
Tuminah ingat betul bahwa ia mendapat makan tiga kali sehari dengan lauk tahu atau tempe, sesekali ikan. Tidak ada penjatahan makanan dalam sistem ianjo di hotel tersebut.
Seingatnya, selama dua tahun dijadikan ianfu, tentara Jepang tidak menggunakan kaputjes, sebutan untuk kondom pada masa penjajahan Jepang.
Kebijakan menjadikan pekerja seks komersial Indonesia sebagai ianfu bermula pada awal tahun 1942, ketika tentara Jepang menyerbu Indonesia, yang saat itu bernama Hindia Belanda.
Soekarno, yang saat itu tengah gencar mengorganisir perjuangan kemerdekaan Indonesia dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Bengkulu, pergi ke Bukittinggi, Sumatra Barat, untuk bertemu dengan petinggi militer Jepang di Sumatra.
Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adams, Soekarno menceritakan tawaran dari Jepang yang menjanjikan kemerdekaan Indonesia sebagai imbalan.
Soekarno akhirnya bersedia bekerja sama dengan pihak militer Jepang dengan menjaga ketertiban rakyat, dengan dalih untuk memuluskan strateginya mencapai kemerdekaan dari belenggu kolonialisme.
Dalam pertemuan dengan Kolonel Fujiyama, petinggi militer Jepang di Sumatra, sempat disinggung mengenai kebutuhan seksual tentara Jepang.
Soekarno kemudian menggagas ide untuk memanfaatkan pekerja seks profesional guna mencegah pemerkosaan gadis-gadis secara liar oleh tentara Jepang, dengan mengumpulkan para pekerja seks di suatu daerah terpencil dan “menempatkan mereka dalam sebuah kamp dengan pagar tinggi di sekelilingnya”.
Setiap tentara Jepang akan diberi kartu dengan ketentuan hanya boleh mengunjungi tempat itu sekali dalam seminggu, kata Soekarno, dengan kartu yang akan dilubangi setiap kali mereka berkunjung.
“Semata-mata sebagai tindakan darurat, demi menjaga para gadis kita dan demi menjaga nama baik negeri kita, aku bermaksud memanfaatkan para pelacur daerah ini,” kata Soekarno, seperti yang dikutip oleh Cindy Adams dalam bukunya.
“Dengan cara ini orang-orang asing itu dapat memuaskan keinginannya dan sebaliknya, para gadis kita tidak diganggu.”
Namun, pada kenyataannya, sebagian besar perempuan yang menghuni ianjo adalah perawan remaja dari desa-desa yang ditipu dan direkrut secara paksa oleh militer Jepang.
Seperti yang dialami Mardiyem, seorang gadis belia berusia 13 tahun, putri dari abdi dalem bangsawan Keraton Yogyakarta.
Ia tertipu oleh iming-iming akan dijadikan pemain sandiwara, bagian dari kelompok sandiwara keliling Pantja Soerja.
Bersama perawan remaja lainnya, Mardiyem dibawa ke Telawang, salah satu basis militer Jepang di pinggiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Di sana, Mardiyem ditempatkan di Asrama Telawang, sebuah ianjo yang ia gambarkan sebagai rumah yang “sangat tertutup dari luar” karena “dikelilingi oleh pagar kayu setinggi tiga meter, ditanami binjai dan pohon kelapa yang besar di pagarnya”.
Di rumah besar itu, mereka dibagi ke dalam kamar-kamar yang sudah dilengkapi dengan dipan, kelambu, dan selimut. Ada juga kastok atau gantungan baju.
Di sudut kamar terdapat sebuah ruangan kecil yang hanya dibatasi oleh kain. Cairan pembersih kemaluan dalam enam botol sudah tersedia.
Para perawan remaja itu kemudian diberi nama Jepang dan nomor di pintu kamar mereka.
“Aku diberi nama ‘Momoye’ dan menempati kamar nomor 11. Sejak saat itu semua orang memanggilku Momoye. Nama Mardiyem telah hilang di Telawang,” ungkap Mardiyem dalam buku biografinya, Momoye Mereka Memanggilku (2007).
Pada malam pertamanya sebagai ianfu, Mardiyem dipaksa melayani enam serdadu Jepang secara berturut-turut. Akibatnya, ia mengalami pendarahan hebat.
“Semenjak itu aku harus menerima kenyataan dipaksa melayani tamu 10-15 orang setiap harinya,” aku Mardiyem dalam buku karya Eka Hindra dan Koichi Kimura tersebut.
Sistem pembayaran dilakukan layaknya membeli karcis bioskop. Ada perbedaan harga yang ditetapkan bagi kalangan serdadu dan perwira Jepang.
Siang hari, untuk pangkat serdadu, mereka harus membayar 2,5 yen, sementara antara pukul 17.00 hingga 24.00 dikenakan biaya 3,5 yen.
Pukul 24.00 hingga pagi hari, untuk pangkat perwira, tarifnya mencapai 12,5 yen.
Namun, uang itu tidak pernah diterima oleh Mardiyem dan ianfu lainnya. Mereka hanya dijanjikan bahwa karcis yang diserahkan kepada para ianfu bisa ditukar dengan uang setelah mereka “pensiun” dan kembali ke daerah asal mereka.
Mardiyem mengaku pernah hamil dan dipaksa menggugurkan janinnya yang berusia lima bulan.
Obat penggugur kandungan yang diberikan ternyata tidak mempan, sehingga jabang bayi dipaksa keluar dengan cara ditekan tanpa bius terlebih dahulu oleh dokter yang memeriksanya.
Lebih dari 50 tahun setelah pengalaman traumatis itu, pada Desember 2000, Mardiyem ditemani oleh Koichi Kimura bertolak ke Tokyo untuk bersaksi di pengadilan rakyat yang diberi nama Tribunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan, menuntut pertanggungjawaban Jepang atas perbudakan seks militer yang mereka lakukan.
Tujuh tahun kemudian, Mardiyem menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2007, tepat pada tahun yang sama saat buku biografinya dirilis.
Penelusuran tentang sejarah ianfu kemudian membawa saya ke Gedung Papak di Desa Gundih, Grobogan, Jawa Tengah.
Bersama Sokiran, juru kunci yang mendampingi, saya memasuki Gedung Papak untuk menggali sejarah bangunan ini dan kaitannya dengan peristiwa ianfu.
Gedung ini dinamakan Gedung Papak karena atapnya datar dan tanpa genting, atau “papak” dalam bahasa Jawa.
Awalnya, gedung ini dibangun sebagai markas besar tentara Belanda pada tahun 1919. Setelah diambil alih oleh Jepang, gedung ini menjadi tangsi atau barak militer Jepang, dan sebagian orang menyebutnya sebagai ianjo.
Setelah Indonesia merdeka, gedung ini dikelola oleh Perhutani dan ditempati oleh administrator sebagai rumah dinas sejak tahun 1953. Namun, pada tahun 1974, sebuah kecelakaan tragis menimpa administrator yang bertugas beserta keluarganya.
“Setelah itu, tidak ada yang berani [menempati],” ujar Sokiran.
Dia kemudian mengajak saya ke lantai dua, yang disebut-sebut sebagai lokasi terjadinya kekerasan seksual puluhan tahun silam.
Sokiran menceritakan pengalamannya bertemu dengan salah seorang penyintas ianfu yang pernah berkunjung ke Gedung Papak.
“[Dia] cerita masalah jadi korban [tentara] Jepang itu sejak umur… yang jelas itu belum dewasa,” tutur pria yang sehari-harinya tinggal tak jauh dari gedung terbengkalai ini.
“Dulu juga [dia] bilang, ‘Ini lho tempat saya jadi korban dulu, tempatnya ini.'”
Penyintas ianfu yang dimaksud oleh Sokiran adalah Sri Sukanti, putri dari seorang wedana di Purwodadi, Jawa Tengah.
Saat itu, ia baru berusia sembilan tahun, namun seorang perwira Jepang telah memperkosanya selama empat hari berturut-turut.
Di kemudian hari, Sri Sukanti dikenal sebagai perempuan termuda yang dijadikan ianfu oleh tentara Jepang.
Sri Sukanti meninggal dunia pada tahun 2017. Setahun sebelumnya, BBC sempat mewawancarainya di rumahnya di Salatiga, Jawa Tengah.
Kepada BBC, ia menceritakan momen ketika ia dipisahkan dari keluarganya. Kala itu, sejumlah tentara Jepang dan perangkat desa datang menemuinya.
“Serdadu [Jepang] dua, Pak RW satu, Pak RT satu. Ayah saya pingsan [saat] saya dibawa, dikira mau dibunuh,” kenang Sri Sukanti.
Setelah “diculik” dari keluarganya, Sri Sukanti dibawa ke Gedung Papak. Di sana, ia harus melayani seorang perwira Jepang.
Sri Sukanti mengaku sering mendapat suntikan agar tidak hamil.
“Biar enggak punya anak. Di sini suntikannya,” ujar Sri Sukanti sambil menunjuk bekas luka di perutnya.
Eka Hindra, seorang penulis lepas yang mendedikasikan lebih dari 20 tahun terakhir untuk meneliti tentang ianfu, mengatakan bahwa perekrutan Sri Sukanti sebagai ianfu adalah kasus “khusus” karena ia hanya melayani Ogawa, seorang perwira Jepang yang sedang transit di Gedung Papak.
Eka Hindra, yang pernah mendampingi Sri Sukanti ke Gedung Papak, mengatakan bahwa selain Sri Sukanti, ada gadis-gadis belia lain yang juga dibawa ke tangsi militer Jepang tersebut.
“Tetapi yang lain untuk serdadu, untuk prajurit yang berpangkat rendah. Sementara Sri Sukanti khusus melayani Ogawa,” jelas Eka Hindra saat saya temui pada akhir Juli lalu.
Selama empat hari berturut-turut, Sri Sukanti berada di Gedung Papak.
“Bisa kita bayangkan apa yang terjadi dalam pemerkosaan itu ketika anak berumur sembilan tahun diperkosa, sehingga ketika Sri Sukanti dipulangkan kembali ke orang tuanya, ia mengalami pendarahan hebat.”
Kepada saya, Eka Hindra memaparkan pola-pola perekrutan ianfu berdasarkan penelitiannya selama lebih dari 20 tahun.
Pertama, pola kekerasan, seperti yang dialami oleh Sri Sukanti. Hal serupa juga terjadi terhadap para perempuan di Gunung Kidul, Yogyakarta.
“Gunung Kidul ini kan waktu itu sangat terpencil, sehingga mereka tidak punya basa-basi atau tekanan untuk melakukan penculikan secara brutal,” kata Eka.
Kedua, pola teror psikologis. Menurut Eka, praktik ini dilakukan dengan merekrut gadis belia yang dimobilisasi dari kampung-kampung ke rumah kepala desa.
“Dimobilisasi dengan kedok akan dipekerjakan oleh tentara Jepang di suatu daerah. Seperti Mardiyem, [yang ditawari] menjadi seniman, menjadi pemain sandiwara.”
“Semakin menuju ke kota, tentara Jepang akan menggunakan pendekatan yang ‘persuasif’,” cetus Eka.
Para perempuan ini kemudian dimobilisasi ke berbagai daerah yang menjadi basis tentara Jepang di Indonesia, termasuk ke Pulau Buru.
Mengapa para perempuan ini direkrut sebagai ianfu dan dikirim ke Pulau Buru yang berjarak lebih dari 2.000 kilometer dari Pulau Jawa?
Pada masa pendudukan Jepang, Pulau Buru memiliki posisi strategis dan digunakan sebagai salah satu pusat pertahanan tentara Jepang selama Perang Asia Pasifik, bagian dari Perang Dunia II yang terjadi di wilayah Asia dan Samudra Pasifik antara tahun 1941 hingga 1945.
Perang Asia Pasifik melibatkan Jepang dan negara-negara Sekutu, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan China.
“Dengan melihat lanskap Perang Asia Pasifik [yang] berbasis di laut, dia (Pulau Buru) menjadi basis tentara Jepang di sana,” ujar Eka.
Di mana ada basis tentara Jepang, kata Eka, di situ pula akan selalu ada praktik ianfu, istilah Jepang yang merujuk pada perempuan yang dipaksa menjadi pekerja seks oleh militer Jepang selama Perang Dunia II, yang sistemik.
“Di mana ada tentara Jepang, di situ kemudian dimobilisasi perempuan-perempuan, apakah itu dari perempuan lokal dari daerah itu sendiri atau dia kemudian ada migrasi, ada perpindahan dari Pulau Jawa, [seperti] yang saya temukan di Pulau Buru,” jelas Eka.
Salah seorang dari ribuan tahanan politik (tapol) yang dibuang ke Pulau Buru, sastrawan Pramoedya Ananta Toer, mendokumentasikan pertemuannya dan tapol lain dengan para perempuan ini dalam bukunya, Perawan Remaja Dalam Cengkeraman Militer.
Jauh sebelum para tapol ini “dibuang” ke Pulau Buru karena dituding terlibat dalam Peristiwa 1965, sudah ada “buangan” lain di pulau terpencil di Indonesia timur ini.
Mereka adalah gadis belia dari Jawa yang dijanjikan akan disekolahkan di Tokyo dan Singapura oleh Jepang pada tahun 1942 hingga 1945.
Di Pulau Buru, para gadis remaja tanpa pengalaman itu diserahkan pada keganasan serdadu Dai Nippon. Di situ pula mereka kehilangan segalanya: kehormatan, cita-cita, harga diri, hubungan dengan dunia luar, dan peradaban.
Saat Jepang menyerah kalah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, masing-masing perempuan ini terpaksa mencari hidup sekenanya, sebagian bahkan mencemplungkan diri dalam kehidupan pribumi setempat dalam ikatan soa, kelompok dalam komunitas adat Alifuru.
Saya berkunjung ke Gondangmanis yang terletak di Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah dan bertemu dengan generasi ketiga penyintas ianfu bernama Tugirah.
“Dia disiksa, dianiaya, terus kalau enggak mau diperkosa, enggak mau ‘disenangi’ itu dipukul,” tutur Anik Sukaningsih, cucu Tugirah, menceritakan apa yang dialami oleh neneknya pada masa penjajahan Jepang.
“[Dia] sembunyi di hutan-hutan sampai lari-lari, jatuh, disiksa lagi. Terus itu diminta ganti-gantian ‘disenangi’, gantian-gantian sampai mbah saya itu perutnya sakit waktu dulu itu.”
Tugirah masih sangat muda saat Jepang masuk ke desanya di Magetan, Jawa Timur, pada tahun 1942.
Menurut Anik, Tugirah sangat piawai menari dan fasih menyanyikan lagu berbahasa Jepang, keterampilan yang ia pelajari saat dididik oleh guru dari Jepang di sekolah pada zaman penjajahan Jepang.
Eka Hindra, penulis yang mengadvokasi isu ianfu di Indonesia, mengatakan bahwa suatu ketika saat Tugirah tengah bermain dengan teman-temannya, dua tentara Jepang menghampiri dan melakukan kekerasan seksual terhadap mereka.
Dua pekan kemudian, kejadian serupa terulang lagi. Meskipun keduanya sudah berontak, mereka tidak berdaya menghadapi tentara Jepang yang memaksa mereka.
Tugirah, bersama sejumlah perempuan belia lainnya, adalah apa yang disebut sebagai ianfu “non-struktural”. Mereka adalah korban kekerasan seksual serdadu Jepang yang tidak sanggup membayar di ianjo.
“Banyak [dari mereka] untuk 3,5 yen saja tidak bisa bayar, akhirnya mereka kemudian memutuskan untuk memperkosa bukan di tempat yang seharusnya, sehingga tidak ada pengecekan kesehatan,” ujar Eka.
“Itulah yang terjadi di beberapa tempat yang saya temui, misalnya di Bogor, di Karanganyar, di Tawangmangu.”
Dia kemudian melanjutkan bahwa dalam manajemen ianjo yang terorganisir, para ianfu ditempatkan dalam kamar-kamar dan kesehatan reproduksi mereka juga diperiksa secara berkala.
Beberapa bahkan disuntik obat anti-hamil dan dipaksa menggugurkan janin mereka.
Setelah pendudukan Jepang berakhir, para mantan ianfu mengalami trauma mendalam dan gangguan fungsi fisik akibat apa yang mereka alami.
“Penyintas ianfu yang mengalami praktik ianfu yang lebih lama periodesasinya itu memang kemudian punya problem dengan alat reproduksinya.”
“Mulai dari tidak bisa punya anak sama sekali, sampai kalau punya anak keguguran,” jelas Eka.
Apa yang dialami oleh perempuan Indonesia, juga dialami oleh para perempuan lain di negara-negara jajahan Jepang pada saat Perang Dunia II. Adapun konsep ianfu telah diterapkan oleh Jepang jauh sebelum diberlakukan di Indonesia.
Setelah tentara Jepang menduduki Kota Nanking dalam invasinya ke China pada tahun 1932, banyak tentara yang menderita penyakit kelamin.
Oleh karena itu, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan baru: prajurit yang menderita penyakit kelamin tidak boleh kembali ke Jepang sampai mereka sembuh, untuk menghindari penyebaran penyakit kelamin ke negara Jepang.
Selain itu, militer Jepang menyediakan perempuan “bersih” untuk tentara Jepang agar mereka tidak terinfeksi penyakit kelamin.
Untuk mengontrol aktivitas seksual para serdadu, sistem ianfu diterapkan di seluruh wilayah Asia Pasifik. Dengan cara ini, keamanan aktivitas seksual prajurit bisa terjamin dan juga bisa menjamin kekuatan militer Jepang.
Sebagai akibat dari kebijakan ini, lebih dari 200.000 perempuan di Asia seperti Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, China, Filipina, Malaysia, Timor Leste, dan Indonesia menderita.
Ahli sejarah Jepang yang pertama kali mempelajari isu ianfu, Profesor Yoshiaki Yoshimi dari Universitas Chuo, juga menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 2.000 kamp atau ianjo yang menampung lebih dari 200.000 perempuan tersebut.
Pada tahun 1991, Kim Han Suk, mantan ianfu asal Korea, menjadi yang pertama memecah keheningan dengan bersaksi di depan umum tentang pengalamannya di Tokyo.
Pada tahun yang sama, Kim Hak Sun mengajukan gugatan hukum, menuntut pemerintah Jepang untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada para korban Jugun Ianfu.
Langkah Kim Hak Sun diikuti oleh para penyintas dari berbagai negara termasuk Indonesia yang menuntut agar pemerintah Jepang menyatakan permintaan maaf, melakukan rehabilitasi, dan memberikan kompensasi.
Seperti halnya di negara-negara korban lainnya, keterlibatan Indonesia dalam pembelaan terhadap korban perbudakan seksual tentara Jepang ini dimulai pada tahun 1992, saat Federasi Asosiasi Pengacara Jepang melakukan kerja sama penelitian tentang korban-korban sistem perbudakan seksual tentara Jepang ini di Indonesia bersama sejumlah kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Tidak ada angka pasti mengenai jumlah perempuan Indonesia yang menjadi korban perbudakan seksual ini.
LBH Jakarta berhasil mendokumentasikan 259 korban, sementara Forum Komunikasi ex Heiho Indonesia mencatat sejumlah 22.454 korban, dan LBH Yogyakarta berhasil mendokumentasikan 11.156 korban.
Pemerintah Jepang mendirikan Asian Women’s Fund untuk membagikan uang santunan yang berasal dari sumbangan masyarakat dan perusahaan-perusahaan pada tahun 1995.
Namun, pemerintah Jepang tetap menolak untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum atas kejahatan perang ini dan bahkan menolak memasukkan masalah perbudakan seksual ini ke dalam buku pelajaran sejarah mereka.
Meskipun Tuminah, Mardiyem, Sri Sukanti, dan Tugirah telah tiada, kisah mereka tetap hidup dan diabadikan dalam berbagai buku serta karya sastra. Namun, tak sedikit penyintas ianfu yang meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan ingatan.
Keberanian Tuminah menyuarakan kekerasan seksual yang dialaminya diabadikan oleh sineas Fanny Chotimah pada tahun 2013 silam, dengan memproduksi film bertajuk “Tum”.
“Kalau misalnya kita niatkan sosok Tuminah sebagai pintu gerbang untuk mempelajari ianfu di Indonesia, mungkin film ini juga berkontribusi yang serupa karena dengan film ini kita bisa membangun nisan dan prasasti yang kita cita-citakan.”
“Jadi setidaknya ada prasasti kecil ini di Makam Tuminah [sebagai] upaya untuk melawan lupa.”
Upaya melawan lupa juga dilakukan oleh aktivis perempuan sekaligus pengajar kajian gender, Dewi Candraningrum, yang secara tidak sengaja melukis puluhan penyintas ianfu.
“Saya mulai melukis tahun 2013, itu juga semua serba kecelakaan. Jadi tidak sengaja, karena saya bertemu dengan mereka, kemudian menyerap trauma mereka. Trauma itu tidak hilang dari saya, kemudian akhirnya saya mulai melukis.”
Lukisan para penyintas ianfu yang dibuat oleh Dewi pun kaya dengan warna mencolok. Dia menjelaskan alasan di baliknya.
“Saya melihat kecenderungan lukisan yang terkait trauma atau kekerasan terhadap perempuan itu cenderung monokromatif.”
“Kemudian saya memilih warna yang mencolok, warna yang radikal, kadang saya beri warna neon, kadang saya tabrakan warna karena harmonisasi warna itu ada pada benturan-benturan warna.”
“Karena saya ingin orang dari jauh ketika melihat itu, terikat batinnya karena warnanya akan menyala.”
Bagaimanapun, bagi Dewi, aktivisme memori dan proses memorialisasi sejarah ianfu perlu diperjuangkan.
Jika sejarah itu dihidupkan kembali dan ditulis secara jujur, menurut Dewi, itu akan berfaedah bagi generasi mendatang agar “kelak ke depan tidak akan terulang kekerasan seksual terhadap perempuan”.
“[Kekerasan seksual] itu berulang ya, misalnya 1942-1945, kemudian 1965, kemudian 1998.”
“Ketika itu mau ditutupi, dihapus atau dijadikan hal tabu, enggak boleh didiskusikan, enggak boleh ditampilkan, otomatis ke depan kita akan menyaksikan kembali kekerasan itu berulang,” jelas Dewi.
Perhutani, pengelola Gedung Papak yang menjadi saksi bisu sejarah ianfu di Indonesia, berniat untuk menjadikan bangunan cagar budaya itu sebagai museum sejarah.
Tak hanya sejarah tentang kejayaan kehutanan di era Hindia Belanda, tapi juga sejarah kelam di era penjajahan Jepang.
“Sejarah kelam bukan berarti nantinya akan membuat pembelajaran yang jelek, bisa juga menjadi pembelajaran yang bagus bahwa seharusnya tidak terjadi seperti itu.”
“Kemudian hal-hal apa yang harus dilakukan supaya terhindar dari seperti itu, atau yang lain mungkin yang bisa, setiap orang bisa menarik pelajaran yang berbeda ketika ada sejarah yang disampaikan.”
Meski gerakan melawan lupa sejarah ianfu tak lekang oleh waktu, harapan kerabat penyintas nyaris pupus.
“Bagaimana ya, soal ianfu itu Indonesia kayak sudah melupakan. Itu bukan lagi menjadi masalah,” ujar Hening, keponakan Tuminah, penyintas ianfu Indonesia yang pertama kali lantang bersuara tentang kesaksiannya menjadi budak seks militer Jepang.
“Jadi kalau mau minta sesuatu berwujud materi atau apa sebuah kegiatan atau badan yang bersifat gender perempuan supaya harkatnya lebih baik itu kayaknya usaha nol, tidak akan didengarkan oleh pemerintah Indonesia.”
“Apalagi situasi politik seperti ini.”