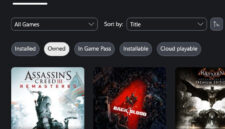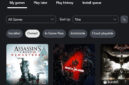“Semoga hari Anda menyenangkan ya.” Sapaan tulus dari seorang ibu paruh baya, warga lokal Kopenhagen, Denmark, itu mengukir kesan mendalam. Saat itu, saya sedang tersesat di jantung kota Kopenhagen, dengan Google Maps yang ‘lumpuh’ akibat ‘titik buta’ sinyal. Tanpa ragu, ibu ini menghentikan langkahnya, bahkan menutup panggilan teleponnya, demi memastikan saya memahami setiap detail rute menuju The Little Mermaid, salah satu ikon wisata terkenal di sana. Bukan sekadar memberi petunjuk, ia hadir dengan perhatian penuh, sebuah kebaikan sederhana yang tak ternilai harganya.
Momen personal nan hangat itu hanyalah secuil refleksi dari kehangatan menyeluruh yang saya rasakan selama beberapa hari menjelajahi Kopenhagen. Sebuah keramahan otentik yang seolah menjelaskan mengapa kota ini, bersama kota-kota lain di Denmark, selalu kokoh bertengger di puncak daftar “kota paling bahagia di dunia” versi berbagai riset dan situs perjalanan. Namun, pertanyaan mendasar kemudian muncul: apa sebenarnya tolok ukur kebahagiaan itu? Dan dari perspektif siapa kebahagiaan tersebut kita ukur?
Warga Denmark yang saya temui memberikan pandangan yang menarik: mereka merasakan betul kehadiran pemerintah dalam menjaga kemakmuran dan kualitas hidup mereka. Ada korelasi kuat antara kesejahteraan (well-being) dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, sebuah temuan yang juga digaungkan oleh berbagai riset terbaru, menegaskan bahwa “mereka merasa pemerintah benar-benar memedulikan mereka.” Meski diketahui Denmark merupakan salah satu negara dengan biaya hidup termahal di Eropa, tingginya pengeluaran ini diimbangi oleh rata-rata pendapatan yang juga substansial, ditopang oleh ketersediaan fasilitas publik yang luar biasa.
Saya menjadi saksi bagaimana masyarakat Denmark, yang rela membayar pajak tinggi, juga merasakan langsung manfaatnya. Pendidikan gratis hingga jenjang magister, fasilitas kesehatan tanpa biaya, sistem transportasi umum yang sangat efisien, serta taman dan ruang rekreasi yang dapat dinikmati cuma-cuma, semuanya adalah buah dari tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan sistem yang berjalan dengan baik.
Pengamatan saya selama di Kopenhagen juga menangkap nuansa kota yang unik: santai namun produktif, ramah namun tanpa kesan berlebihan, serta sentuhan aristokratis yang kental namun jauh dari kesan sombong. Detail-detail kecil ini seolah menjadi kepingan puzzle yang melengkapi pemahaman saya tentang definisi kebahagiaan ala Denmark.
Di berbagai restoran, saya menyaksikan warga lokal bercengkrama dengan tenang, tanpa tergesa-gesa. Di transportasi umum, suasana hening yang tercipta bukan karena ketidakpedulian, melainkan manifestasi dari rasa saling menghormati ruang pribadi. Bahkan para petugas yang saya temui, dari stasiun hingga toko dan tempat wisata, memancarkan keramahan yang tulus, jauh melampaui sekadar tuntutan profesionalisme.
Sebagai seorang turis, saya merasa sangat nyaman berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau meminta petunjuk saat tersesat. Kebiasaan multibahasa warga Denmark dalam keseharian mereka, terutama di sektor kuliner dan tempat-tempat umum, sangat membantu. Namun, yang paling mengesankan adalah cara mereka menghargai komunikasi: mereka tidak hanya memberikan jawaban, melainkan memastikan lawan bicara benar-benar memahami informasi yang disampaikan.
Esensi menghargai dan memedulikan orang lain inilah, menurut pandangan saya, yang menjadi salah satu kunci kebahagiaan yang sering terlewatkan. Di tengah era yang kian individualistis, sikap seperti ini menjadi aset yang langka dan sangat berharga.
Apa yang saya rasakan di Denmark selaras dengan temuan *Happiness Report 2025*, yang mengidentifikasi beberapa elemen kunci kebahagiaan suatu negara: *caring & sharing*, *social connection*, *trust*, *pro-social behavior*, dan *giving to others*. Semua elemen ini secara nyata saya alami selama perjalanan di Denmark.
Fakta menarik lain datang dari *Harvard Report 2017* yang diterbitkan melalui *The Harvard Gazette*: kesepian memiliki dampak merusak jiwa dan raga yang setara dengan rokok atau alkohol. Barangkali, di Kopenhagen, di mana kota-kota tertata rapi namun jiwa kadang terasa sunyi, banyak hal esensial tersedia secara gratis sebagai ‘penawar’ kesepian dan ‘pemulih’ sanubari.
Namun, esensi tulisan ini bukanlah ajakan untuk mempromosikan negara lain. Sebaliknya, ini adalah sebuah perenungan mendalam bahwa Indonesia, dengan kekayaan alam dan budayanya yang luar biasa, sesungguhnya memiliki potensi tak terbatas untuk mewujudkan tingkat kebahagiaan serupa. Pertanyaan krusialnya kini adalah: bagaimana kita dapat menumbuhkan kembali budaya *caring & sharing*, membangun fondasi kepercayaan sosial, dan menciptakan ruang-ruang yang memungkinkan setiap individu untuk terhubung dengan tulus?
Pada akhirnya, mungkin kunci sejati kebahagiaan Kopenhagen tidak semata terletak pada infrastruktur modern atau sistem pemerintahan yang kokoh, melainkan pada kesediaan setiap individu untuk mengucapkan “semoga hari Anda menyenangkan” dengan ketulusan kepada orang asing yang membutuhkan bantuan. Sebuah pelajaran sederhana yang universal, dan dapat kita terapkan di mana pun kita berada.